[W . RUINEN]
- Kata Pengantar
Tulisan yang kami terjemahkan ini sebenarnya adalah hasil “kritik” atas “kritik”, “tinjauan” terhadap “tinjauan”. Semuanya berawal dari riview atau tinjauan yang “bernada” kritik dari Johan Philip Duyvendak, seorang sarjana yang tesisnya berjudul Kakean-Genootschap van Seran terhadap buku Bij de Berg-Alfoeren op West-Ceram dari G. De Vries, seorang militer yang pernah bertugas di Hunitetu, Seram Barat. Tinjauan Duyvendak ini sepanjang 2 halaman. Tinjauan ini kemudian mendapat tanggapan dari W. Ruinen, seorang militer yang juga pernah bertugas di Seram Barat, yang kemudian menjadi arsiparis pada Moluccan Instituut dalam tahun 1928/1929.
Tinjauan atau tanggapan W. Ruinen ini berjudul Ethnografische Gegevens van West-Ceram, yang dimuat di Majalah Mensch en Maatschappij, volume 5, nomor 3, tahun 1929, halaman 220-232. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tulisan sepanjang 13 halaman dengan 13 catatan kaki ini, adalah tinjauan atau tanggapan dari W. Ruinen terhadap tinjauan J.Ph. Duyvendak.
Kami mencoba menerjemahkan
tulisan ini, menambahkan sedikit catatan tambahan dan ilustrasi, dimana pada
naskah aslinya, sang penulis tidak “memasukan” gambar/foto. Tujuan kami
hanyalah sederhana, menyajikan tulisan untuk dibaca, yang dalam konteks tulisan
ini, adalah untuk memperlihatkan bahwa perbedaan pendapat, atau perspektif,
merupakan hal yang lumrah dan “wajib” dalam dunia akademis, dan sebaiknya perlu
dilestarikan. Tentunya, meski kepala kita sama, tetapi isi kepalanya tidak
selalu harus seragam. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat untuk memperluas
pengetahuan dan wawasan kesejarahan kita.
- Terjemahan
Dalam majalah edisi November inia, Dr. J.Ph. Duyvendakb memberikan pembahasanc tentang buku karya G. de Vriesd terbitan tahun 1927, “Bij de Berg-Alfoeren op West-Ceram”e - sebuah pembahasan yang menurut sang peresensi yang meyakini bahwa buku tersebut pasti mempunyai tujuan ganda, terfokus pada “niat kedua yang tak terucapkan: nilai sebagai kontribusi ilmiah”.
Meskipun mungkin ada berbagai keberatan terhadap pilihan dan perumusan titik awal ini, keberatan keberatan tersebut dapat dikesampingkan di sini karena dianggap tidak terlalu relevan.
Seperti yang dilakukan banyak orang lain di Hindia Belanda—para pejabat, perwira, pengelana sebelumnya ketika menggambarkan suatu bangsa yang pernah mereka temui, De Vries juga, ketika ia mulai memproses apa yang telah ia amati dan dengar selama tinggal lama di antara suatu bangsa yang relatif kurang dikenal, dengan naif melangkah ke dalam wilayah yang telah ditandai oleh etnologi sebagai bidang studinya.
Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa para praktisi ilmu ini merasa terpanggil untuk mengevaluasi nilai pernyataan-pernyataannya. Dapat dipahami pula bahwa Dr. Duyvendak mengambil tugas ini. Tulisannya tahun 1926 tentang Kakean-Genootschap van Seran [masyarakat kakihan] menunjukkan keterlibatan yang mendalam dengan literatur dan masalah-masalah etnologis di Seram, dan memiliki signifikansi yang sepenuhnya diakui bahkan oleh mereka yang tidak atau tidak dapat sepenuhnya setuju dengan kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakannya. Dengan demikian, penilaiannya terhadap nilai ilmiah dari sebuah karya yang menggambarkan masyarakat Seram tentu saja berbobot.
Akan tetapi, dalam menyampaikan penilaian ini, terlalu sedikit pertimbangan diberikan pada kemungkinan bahwa, selain dari apa yang sudah tercatat dalam literatur, mungkin ada juga data lain yang belum dipublikasikan yang diketahui oleh mereka yang bekerja atau pernah bekerja di Ceram. Oleh karena itu, sangat disesalkan bahwa Dr. Duyvendak —yang pernah mengasumsikan tujuan ilmiah "yang tidak disebutkan" dari karya tersebut—merasa terpaksa dengan berbagai alasan untuk menyangkal nilai pernyataan De Vries, dan di beberapa tempat bahkan meragukan keakuratannya.
Kini, sejarah penelitian etnologi di Kepulauan Indonesia mencatat lebih banyak kontroversi seperti itu antara peneliti lapangan—yang sering kali tidak memiliki akses ke literatur—dan peneliti di perpustakaan dan museum, yang tidak dapat terlibat langsung dengan materi hidup. Dan seperti yang sering terjadi dalam kasus seperti itu, mungkin lebih baik membiarkan waktu menentukan nilai yang tepat dari buku dan kritik (yang, dalam literatur Maluku, sering kali menghasilkan hasil yang mengejutkan)—seandainya saja, dalam kasus ini, penyelesaian yang lebih cepat lebih baik.
Memang, evolusi yang dialami penduduk pedalaman Seram Barat terus berlanjut dengan mantap. Banyak hal yang mampu bertahan hampir tidak berubah selama berabad-abad di antara orang-orang ini yang hidup dalam kemerdekaan penuh—runtuh setelah, lebih dari dua puluh tahun yang lalu, pembentukan otoritas Belanda dimulai. Berbagai lembaga dan adat istiadat harus dihapuskan atau diubah, dan melalui pengenalan sistem administrasi yang selaras dengan bentuk pemerintahan yang diterapkan di seluruh wilayah, penyatuan kelompok-kelompok yang tersebar ke dalam desa-desa, dan berbagai tindakan lainnya, fondasi masyarakat primitif ini mengalami transformasi total.
Meski demikian, bagi mereka yang berkesempatan membandingkan keadaan aslinya dengan situasi saat ini, tetap mengherankan betapa cepatnya karakter masyarakat ini berubah dan betapa mudahnya nama, lembaga, dan konsep baru berakar—bahkan dalam menghadapi perlawanan berulang yang dipicu oleh reformasi yang dipaksakan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kristenisasi dan pendidikan telah berkontribusi dalam mempercepat laju evolusi ini. Dalam situasi seperti ini, menjadi penting untuk mencatat apa pun yang masih diketahui tentang adat istiadat dan tradisi leluhur secepat mungkin, sehingga dapat melestarikan apa pun yang masih dapat diselamatkan.
Tentu saja, akan lebih baik jika tugas ini dapat dipercayakan kepada seorang etnolog. Akan tetapi, selama hal ini lebih merupakan keinginan yang saleh daripada kemungkinan yang realistis, tampaknya tidak praktis untuk menolak temuan-temuan dari mereka yang, demi memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka dengan baik, telah dipaksa untuk melakukan penelitian mereka selengkap mungkin. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir, penyelidikan semacam itu telah mampu menghasilkan hasil yang lebih baik, karena setelah penindasan pemberontakan terakhir (1914–1916) dan eksplorasi intensif berikutnya di pedalaman, penduduk secara bertahap mulai menunjukkan keterbukaan yang lebih besar. Kini orang tidak selalu menjumpai kerahasiaan yang sama, yang sebelumnya juga dihadapi oleh mereka yang sebelumnya memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat ketika mencoba—secara langsung atau tidak langsung—untuk memperoleh informasi tentang konsep-konsep keagamaan dan lembaga-lembaga sosial.
Data yang dapat dikumpulkan dalam beberapa tahun terakhir ini belum dipublikasikan dan hanya dapat ditemukan dalam memorandum, catatan, atau laporan pejabat dan perwira yang bertugas di Seram Barat1. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menawarkan beberapa klarifikasi—yang sebagian didasarkan pada data tersebut—untuk menentukan nilai karya De Vries dengan lebih baik, dan dengan demikian mengatasi potensi kerugian yang dapat timbul dari penilaian yang diberikan: yaitu, kerugian bahwa pengamatannya mungkin tidak menerima perhatian yang layak².
Hasil seperti itu tentu sangat disayangkan, sebab hal ini akan kembali mengurungkan niat untuk memulai kajian perbandingan dan pelengkap mengenai Seram itu sendiri dalam waktu dekat. Untuk menilai dengan tepat nilai pernyataan De Vries, mungkin paling praktis untuk terlebih dahulu memeriksa keberatan yang diajukan terhadapnya oleh Dr. Duyvendak .
Salah satu keberatan tersebut adalah bahwa dasar buku tersebut dianggap tidak pasti. "Tidak jelas," tulis pengulas, "apa yang menjadi dasar penulis dalam membuat laporannya. Apakah ia memahami bahasa setempat? Apa yang ia ambil dari literatur dan apa yang ia amati sendiri?" Kurangnya pemahaman mengenai tugas seorang perwira di wilayah yang belum sepenuhnya aman, yang tersirat dalam pertanyaan pertanyaan ini, membuat jawaban yang agak rinci diperlukan.
De Vries bertugas selama hampir dua setengah tahun sebagai komandan bivak di Honitetoef, salah satu dari dua bivak yang tetap ditempati di Seram Barat setelah penindasan pemberontakan terakhir pada tahun 1916. Komandan bivak bertindak sebagai perwakilan dan kuasa hukum dari petugas distrik Seram Barat dalam wilayah patroli yang ditugaskan kepadanya. Dalam kapasitas ini, ia memegang peran yang bertanggung jawab dan multifaset, membawanya ke dalam kontak harian dengan penduduk—baik di posnya maupun selama patroli yang sering, yang sering kali melibatkan tinggal lebih atau kurang lama di desa-desa lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas yang diberikan, mengendalikan pendaftaran, menilai pajak, dan melakukan investigasi awal atas masalah peradilan dan masalah lainnya.
Pada saat saya meninggalkan Seram Barat pada tahun 1919g, arsip kecil di Honitetoe sudah berisi informasi berharga tentang populasi dan bahasa Honitetoe dan Ahiolo. Data ini, yang tidak dikumpulkan untuk dipublikasikan tetapi murni untuk keperluan pemerintahan dan administrasi peradilan, berulang kali diuji dan dilengkapi. Hasilnya, komandan bivak berikutnya dapat dengan cepat mengenal adat istiadat setempat dan bahasa daerah. Poin terakhir ini, pada kenyataannya, penting, karena penerjemah tidak selalu tersedia.
Oleh karena itu, pernyataan De Vries harus dianggap sebagai hasil penelitian dan pengamatannya sendiri—yang sebagian didasarkan pada informasi sebelumnya yang dikumpulkan oleh para pendahulunya, dan sebagian lagi pada apa yang sudah tersedia dalam literatur utama. Tentu saja, tinjauan literatur yang lengkap tidak mungkin dilakukan di lokasi yang terisolasi dan sulit dijangkau seperti Honitetoe. Namun, melalui kutipan dan referensi dalam bukunya, De Vries menunjukkan bahwa ia familier dengan karya Sachseh, Tauerni, dan publikasi Seran dari Encyclopaedic Bureau.
Keberatan lainnya sebagian besar didasarkan pada perbedaan antara pernyataannya dan informasi yang ditemukan dalam literatur Ceram lainnya. Akan tetapi, hal itu harus ditangani dengan hati-hati—seperti yang berulang kali ditunjukkan Dr. Duyvendak dalam penelitiannya tentang masyarakat kakihan —bahwa data ini tidak selalu dapat diandalkan. Ia juga menekankan banyaknya kesenjangan dalam pengetahuan etnografi kita tentang Seram. Misalnya, pada halaman 7 karyanya, ia dengan senang hati mengutip kata-kata Prof. Nieuwenhuisj dari laporan tahun 1914 tentang ekspedisi Seram yang diusulkan oleh Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Duyvendak kemudian mencatat bahwa vonis tentang pengetahuan etnografi kita yang tidak memadai masih berlaku, bahkan setelah publikasi beberapa tahun terakhir. Lebih jauh, pada halaman 30, ia menulis—merujuk pada pernyataan Prof. van Vollenhovenk bahwa di Maluku, orang Ambon, “organisasi sosial yang murni teritorial belum pernah tercapai di mana pun”—bahwa “Apa yang sebenarnya telah tercapai lebih sulit untuk ditentukan. Di samping sifat laporan yang tidak sistematis, hal ini disebabkan oleh penggunaan istilah Melayu yang membingungkan untuk istilah adat dan penggunaan kata-kata yang sama sekali anarkis seperti “keluarga”, “marga”, “masyarakat” dll., sementara pengaruh intervensi pemerintah juga tidak selalu dapat dibedakan dengan jelas”.
Ini sepenuhnya akurat.
Lebih jauh, sudah diketahui bahwa pelaporan tersebut kurang dapat diandalkan jika menyangkut wilayah pedalaman Seram Barat, yang hingga baru-baru ini tertutup bagi penelitian serius apa pun. Bahkan setelah penghalang ini disingkirkan—kira-kira dua puluh tahun yang lalu—pengetahuan etnografis tentang wilayah ini hanya dapat berkembang perlahan, karena adanya perlawanan yang berulang dan keengganan serta ketakutan di antara penduduk untuk berbicara tentang agama dan lembaga mereka, sebagian besar di bawah pengaruh masyarakat kakihan. Akibatnya, dalam sebagian besar literatur, informasi yang berkaitan dengan Seram Barat terutama diperoleh dari laporan penduduk desa-desa pesisir, atau dari kontak yang sangat singkat dengan beberapa individu atau kelompok dari suku-suku pegunungan. Bahkan dalam publikasi yang lebih baru, masih ada fokus yang tidak proporsional pada penduduk pesisir. Akibatnya, adat istiadat, lembaga, dan gagasan dari pesisir—yang sering kali sangat berubah di bawah pengaruh berbagai aliran budaya—sering kali digambarkan seolah-olah juga berlaku untuk suku-suku pegunungan.
Ilustrasi yang jelas tentang hal ini dapat ditemukan dalam daftar pustaka yang dikutip di akhir buku Dr. Duyvendak. Di antara karya-karya yang tercantum, tidak ada satu pun yang membahas secara eksklusif tentang penduduk pedalaman—yaitu, segmen populasi tempat lembaga teritorial dan adat istiadat lama dilestarikan dalam bentuk paling murni³.
Dari sekitar 40 penulis yang dikutipnya, hanya 6 yang pernah mengunjungi pedalaman Seram Barat—yaitu, Prof. Martinl (selama 4 sampai 5 hari), Sachse, van Hecht Muntingh Napjusm dalam beberapa ekspedisi, dan anggota Ekspedisi Maluku Freiburg: Deningern, Stresemanno, dan Tauern. Masalah dengan deskripsi umum mengenai penduduk pesisir dan pedalaman ini telah dibahas di atas. Dalam banyak kasus, tidak jelas apa yang asli dan apa yang telah diubah. Lembaga-lembaga yang diperkenalkan oleh pemerintah digambarkan seolah-olah merupakan lembaga asli. Penggunaan kata-kata Melayu dan Melayu-Ambon untuk lembaga-lembaga lokal menambah kebingungan. Kadang-kadang bahkan tampak seolah-olah istilah istilah asli telah sepenuhnya digantikan—ini mungkin juga disebabkan oleh kecenderungan orang Alfur, ketika berbicara dengan orang asing, untuk dengan bangga memamerkan pengetahuannya dengan menggunakan kata-kata asing yang tidak dikenal.
Apakah masih perlu diperdebatkan bahwa hanya deskripsi yang baik dan akurat tentang suku-suku pedalaman di Seram Barat yang dapat memberikan kejelasan—dan dengan demikian landasan yang kuat bagi pemahaman etnografis wilayah ini?.
Sejauh ini, kami hanya memiliki dua publikasi yang membahas secara eksklusif kelompok populasi ini: Het binnenland van West-Ceram en zijn bewoners oleh WHF Giel⁴/p, dan sekarang karya De Vries. Inilah yang terutama mendefinisikan nilai buku De Vries. Gambaran yang dilukiskannya tentang penduduk pedalaman dan lembaga serta adat istiadat mereka lebih jelas dan lebih tepat daripada deskripsi umum tentang pesisir dan pedalaman. Karena alasan ini khususnya, informasi yang diberikannya layak mendapat perhatian setiap peneliti. Tanpa mengikuti ulasan Dr. Duyvendak poin demi poin, saya akan menawarkan beberapa klarifikasi di sini mengenai pernyataan De Vries, sebagai tanggapan terhadap beberapa kritik utama yang diajukan.
Hal ini terutama dan terutama menyangkut loema-inai .
Untuk memahami persoalan ini dengan benar, saya terpaksa—meskipun enggan—untuk merujuk pada tindakan dan pengamatan saya sendiri. Ketidakpastian yang menyelimuti aspek-aspek yang paling sederhana sekalipun dari masyarakat Seram Barat dapat dilihat, misalnya, dalam perbedaan pandangan tentang tujuan dan penamaan bangunan-bangunan yang dalam literatur sering disebut dengan nama-nama non-pribumi yaitu “baileo” dan “roemah poesaka”.
Mengenai rumah-pusaka di Seram Barat, hanya sedikit disebutkan secara singkat dalam literatur⁵; namun, dalam dokumen resmi, muncul laporan yang agak lebih rinci. Beberapa catatan yang saya buat dari memorandum tahun 1916 tentang masyarakat kakihanq oleh Letnan Satu WKH Feuilletau de Bruyn—yang bekerja selama beberapa tahun di Seram Baratr—dapat diringkas sebagai berikut:
“Di rumah pusaka, nitu (roh leluhur) dari para leluhur pendiri dipuja. Awalnya, persembahan untuk nitu dibuat di atas piring-piring tua. Seiring berjalannya waktu, piring-piring ini mulai dianggap sebagai tempat tinggal nitu, dan akhirnya, benda-benda itu sendiri disembah sebagai jimat. Selain nitu keluarga ini , roh orang-orang yang telah meninggal lainnya juga dipuja di rumah pusaka. Sangat diperhatikan agar piring-piring dan benda-benda pusaka lainnya yang disimpan di rumah-rumah ini tidak basah, karena hal ini diyakini dapat menyebabkan penyakit dan bencana alam. Namun, ketika rumah perlu diberi atap baru, kepala harus diambil. Setelah kepala yang terpenggal digantung di pilar utama rumah pusaka, tahoeri (terompet) ditiup untuk memanggil nitu dan roh orang mati, yang diperkirakan telah meninggalkan rumah. Baru setelah itu atap baru dapat dimulai.”
Kemungkinan besar kepercayaan inilah yang mendorong pemerintah, antara tahun 1910 dan 1914 (saya tidak dapat memberikan tanggal yang lebih tepat), untuk mengeluarkan perintah agar semua rumah pusaka dibongkar. Pertimbangan bahwa hal ini akan menghilangkan motif berulang untuk memburu kepala—karena atap jerami masyarakat primitif perlu sering diganti—mungkin memainkan peran yang menentukan.
Seperti yang kemudian terbukti, tindakan ini memicu kemarahan yang signifikan dan menjadi salah satu penyebab kerusuhan yang berujung pada pemberontakan tahun 1914. Tindakan yang lebih bijaksana mungkin adalah mencoba mengganti persembahan kepala—misalnya, dengan membujuk para pemimpin setempat, seperti yang telah dilakukan pada tahun 1906 dalam kasus perburuan kepala setelah kematian salah satu elake (kepala/pemimpin) klan, untuk mengganti kepala dengan piring atau benda lain yang sesuai. Seberapa cepat kebiasaan pengganti tersebut dapat diadopsi ditunjukkan dalam sebuah laporan dari sepuluh tahun kemudian dalam memorandum yang disebutkan di atas oleh Feuilletau de Bruyn:
“Dulu, saat seorang elake meninggal, kepala selalu diambil/dipotong. Sekarang, tradisi ini sudah tidak berlaku lagi, dan orang-orang tinggal meminta piring dari desa tetangga”.
Bagaimanapun juga, larangan itu tetap diberlakukan; rumah-rumah pusaka dirobohkan atau dibakar, dan benda-benda pusaka disembunyikan oleh penduduk di bawah naungan di hutan atau dikubur di berbagai tempat terpencil.
Hal ini menjelaskan, setidaknya sebagian, pernyataan yang saling bertentangan tentang rumah pusaka yang ditemukan pada halaman 109 buku [berjudul] Seran ( Mededelingen Encyclopaedisch Bureau, 1923). Mengenai desa-desa pesisir, disebutkan:
“Setiap soa (klan atau garis keturunan) yang membentuk desa harus memiliki baileo ( héline atau sisine ) sendiri— baileo pusaka, sebuah kenangan simbolis tentang desa pegunungan tempat orang-orang dulu tinggal. Sebagian besar sisine ini sudah tidak ada lagi.”
Kemudian berlanjut:
“Di antara suku pegunungan, rumah pusaka masih ada—yaitu, rumah (kadang-kadang hanya tempat berteduh) tempat pusaka soa dipelihara”.
Berikut ini adalah catatan dari Letnan Sierevelts, yang bertugas selama bertahun-tahun sebagai komandan bivak di Riring :
“Di rumah pusaka (= tempat tinggal yang tetap), pusaka itu milik orang kaya atau keluarga yang makmur, bukan milik soa .”
Bahwa pernyataan-pernyataan tersebut—yang mencerminkan pandangan yang dianut sekitar tahun 1918 di Seram Barat—bertentangan dan tidak sepenuhnya benar maupun lengkap adalah jelas, dan juga ditunjukkan dengan penggunaan berbagai istilah non-pribumi. Pada bulan September tahun yang sama [1918], penulis ini, selama ekspedisi ke pedalaman, mencoba—salah satu caranya—untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai rumah-rumah pusaka, juga sebagai tanggapan atas permintaan dari beberapa desa pegunungan untuk diizinkan membangun kembali rumah-rumah tersebut.
Investigasi ini, setelah ketidakpercayaan terhadap niat pemerintah (yang tidak sepenuhnya tidak beralasan, mengingat peristiwa sebelum tahun 1914) telah diatasi, membuahkan hasil yang mengejutkan. Informasi yang saya peroleh dapat diringkas sebagai berikut: Di Moerikaoe, saya diberi nama loema-pohone untuk rumah-rumah ini; namun, istilah loema-inai, yang lebih umum digunakan di kalangan masyarakat Alune dan Wemale , juga dikenal di sana⁶. Loema-inai tidak hanya dimaksudkan untuk menyimpan pusaka keluarga (piring, guci, mangkuk, piring, gong, dll.), tetapi juga menjadi tempat di mana persembahan diberikan kepada roh anggota keluarga yang telah meninggal.
Kelompok keluarga itu sendiri juga disebut loema-inai. Setiap loema-inai (baik rumah maupun kelompok keluarga) memiliki nama yang berbeda. Jumlah anggota dalam setiap kelompok sangat bervariasi, tetapi dalam beberapa kasus cukup besar. Rumah itu bukan sisine ( baileo ), melainkan rumah biasa, yang dapat diakses setiap saat oleh wanita dan anak-anak, dan harus terus dihuni—atau lebih tepatnya, “dijaga.” Peran “wali” bersifat turun-temurun. Apakah orang ini merupakan keturunan dari leluhur pendiri keluarga? Saya tidak dapat memastikannya. Sejauh yang saya ketahui, mungkin saja wali tersebut juga seorang maoewen (pendeta), tetapi status ini bukan merupakan persyaratan yang diperlukan untuk peran tersebut. Secara umum dibantah bahwa perburuan kepala diperlukan untuk membangun kembali atau memasang atap baru pada loema-inai.
Selain itu, informasi yang saya kumpulkan memberikan data menarik tentang asal-usul dan organisasi populasi, dan menunjuk pada struktur silsilah yang lebih kuat daripada yang sebelumnya diasumsikan untuk Ceram Barat. Sayangnya, karena serangkaian keadaan yang tidak menguntungkan, rencana untuk menyelesaikan penelitian ini tidak dapat dilaksanakan. Ketika saya pergi pada tahun 1919, masalah loema -inai masih belum terselesaikan dan harus diserahkan kepada pengganti saya.
Kesan yang saya peroleh adalah bahwa penduduk pedalaman Seram Barat terbagi atas kelompok-kelompok kekerabatan (loema-inai), dan bahwa hena (suku atau kampung) terbentuk dari penyatuan beberapa loema-inai. Argumen yang menentang penafsiran ini dapat ditarik dari klasifikasi soa yang sekarang digunakan untuk desa-desa. Akan tetapi, pada masa jabatan pertama saya di Seram Barat, istilah soa dan kepala-soa belum dikenal di pedalaman. Istilah-istilah tersebut diperkenalkan ketika, pada tahun 1907, pemerintahan desa ditata ulang sesuai dengan sistem yang digunakan di wilayah-wilayah yang diperintah langsung oleh karesidenan Ambon. Pada saat saya kembali ke Seram Barat pada tahun 1916, istilah-istilah tersebut sudah mengakar sepenuhnya.
Apakah kelompok-kelompok yang mirip dengan soa di bagian lain wilayah hukum Ambon pada awalnya ada di masyarakat ini, saya tidak dapat mengatakannya. Yang pasti adalah bahwa nama-nama loema-inai umumnya tidak sesuai dengan nama-nama soa ; mereka hanya kadang-kadang identik. Lebih jauh, jumlah loema-inai di sebuah desa berbeda dari jumlah soa —dalam kebanyakan kasus, ada lebih banyak loema-inai.
Namun, ini tidak berarti banyak dengan sendirinya. Ketika menunjuk pemimpin daerah, keputusan sering dibuat secara sewenang-wenang. Kadang-kadang pemegang gelar sebelumnya (misalnya, latu, kapitan, alamanan) diangkat menjadi regent atau kepala soa, tetapi ada juga orang yang ditunjuk karena mereka berbicara sedikit bahasa Melayu atau menonjol. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa kelompok administratif yang diciptakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan organisasi sosial aslinya. Kita juga harus mengingat kecenderungan suku Alfur untuk memberi nama pada berbagai hal: tempat-tempat di hutan, bekas rumah atau lokasi ladang, dan bahkan baileo atau loema-inai sering kali punya nama sendiri.
Meskipun dapat dipahami bahwa Dr. Duyvendak, berdasarkan data yang tersedia baginya, menyimpulkan bahwa loema-inai yang pertama kali dijelaskan oleh De Vries hanyalah baileo-soa yang awalnya dimiliki dan masih dimiliki oleh setiap soa, tetap saja ada beberapa keberatan terhadap klaim ini. Kita mengenal baileo-soa hanya dari desa-desa pesisir. Di antara suku-suku pegunungan, hanya ada dua baileo : sisilatu dan sisianakota. Akan tetapi, sangat mungkin bahwa rumah-rumah yang disebut baileo-soa di desa-desa pesisir berkembang dari loema-inai. Penafsiran ini didukung, antara lain, oleh catatan yang disebutkan sebelumnya dalam Seran (halaman 226 di atas), yang menyamakan istilah baileo-soa dan baileo-pusaka.
Namun, hal ini tidak sesuai dengan situasi yang saya temui di pedalaman pada tahun 1918, maupun dengan deskripsi De Vries sendiri. Ketika De Vries tiba di Seram pada tahun 1921, sistem soa sudah sangat mapan sehingga ia juga menganggapnya sebagai sistem asli—pandangan yang saat ini tidak dapat saya dukung⁸. Hanya penelitian yang cermat yang dapat menjelaskan pertanyaan ini dan pertanyaan lainnya mengenai loema-inai dan struktur loema-inai. Dengan menyusun, misalnya, ikhtisar soa dan loema-inai di setiap desa⁹ dan meneliti bagaimana dan mengapa mereka diberi nama, kita pasti bisa memperoleh wawasan lebih luas tentang masalah ini. Penelitian tersebut mungkin akan menghasilkan hasil yang lebih baik saat ini, karena selama beberapa tahun pemerintah telah mengizinkan pembangunan kembali loema-inai, asalkan dibangun di dalam desa.
Beberapa rincian spesifik yang muncul pada saat itu patut disebutkan di sini.
Klan Honitetoe diketahui tersebar di sejumlah desa: desa utama dengan nama yang sama, dan dusun dusun atau pemukiman yang lebih kecil di Oeraoe, Oersana, Roematita, Imahatai, Solehatai, dan Lakoeboetoei. Di desa utama, ada tujuh loema-inai, sedangkan masing-masing desa yang lebih kecil hanya memiliki satu. Dengan demikian, penduduk pemukiman yang lebih kecil ini masing-masing membentuk satu kelompok keluarga, yang ditambahkan dengan para lelaki dari desa lain yang menikah dengan komunitas tersebut dan—menurut adat setempat—pindah bersama istri mereka.
Di desa-desa Alune di wilayah yang sama (dulu distrik administratif Tala), situasinya agak berbeda. Di sini, loema-inai hanya ditemukan di desa utama. Misalnya, penduduk Roembatoe dan Roemberoe, yang termasuk clan Manoesa-Manoewe, tidak memiliki loema-inai di desa mereka sendiri, tetapi di desa utama Manoesa-Manoewe. Demikian pula, Noeroeë dan Melilia tidak memiliki loema-inai di desa mereka, tetapi di desa induk mereka, Niniari dan Roemasoal¹⁰.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa data yang diberikan oleh De Vries mengenai loema-inai dan struktur loema-inai —meski menurut Dr. Duyvendak , kurang memiliki nilai ilmiah—bagaimanapun juga, data tersebut sangat penting, karena memberikan gambaran yang lebih jelas tentang organisasi sosial dan hakikat lembaga adat di Seram Barat. Dan bahkan jika beberapa tambahan atau koreksi terbukti diperlukan, orang harus ingat bahwa pengetahuan kita tentang etnografi wilayah-wilayah ini hanya mampu berkembang secara perlahan dan tersendat-sendat.
Keakuratan laporan De Vries mengenai adat istiadat Wemale —yang menunjukkan bahwa sistem kekerabatan di antara kelompok ini adalah matrilineal—dipertanyakan oleh Dr. Duyvendak. Jadi beberapa klarifikasi juga diperlukan di sini. Telah diketahui bahwa kaum Wemale tidak membayar mas kawin untuk perkawinan dalam klan¹¹. Beberapa aturan warisan yang dilaporkan oleh De Vries telah dipatuhi sebelumnya oleh pejabat dan perwira di Seram Barat. Akan tetapi, sebagian besar informasi mengenai adat perkawinan dan hukum waris sebelumnya tidak diketahui atau hanya kurang dipahami.
Apakah pengetahuan etnografi kita saat ini tentang Seram Barat begitu dapat diandalkan sehingga kita harus, seperti yang tampaknya disarankan oleh Dr. Duyvendak, mengabaikan pernyataan-pernyataan ini sebagai generalisasi yang salah dari satu kasus yang diamati?
Tidak ada alasan yang kuat untuk keputusan yang meremehkan tersebut. Lebih jauh, De Vries, selama masa tinggalnya yang panjang di dalam negeri, mampu mengamati banyak kasus, dan bahkan harus menyelidikinya sesuai dengan tugas resminya—yang membuatnya sangat mungkin bahwa ia secara akurat menyajikan fakta-fakta, bahkan jika kesimpulannya mungkin dinyatakan terlalu kuat.
Dan dia tidak sendirian dalam temuannya.
Deskripsi onderafdeeling Amahai, diambil dari laporan serah terima administratift, Gezaghebber GL Tichelmanu (yang mengakhiri tugasnya pada tahun 1923)¹², memuat catatan berikut:
“Kepemilikan
tanah berkaitan dengan hukum keluarga dan kekerabatan, yang secara umum
bersifat patriarki, namun, mungkin di bawah pengaruh hukum tetangga, Lembaga
Alfur —atau sisa-sisanya—menunjukkan nuansa matriarki”. “Alfur murni,
setidaknya di desa-desa Patasiwa-hitam yang termasuk dalam wilayah Tala,
properti doesoen (kebun) diwariskan kepada perempuan. Laki-laki
diharapkan, melalui pernikahan, untuk memperoleh akses ke doesoen yang
dibutuhkan untuk penghidupannya. Jika tidak ada mahar yang dibayarkan, anak-anak
mengambil fam (nama keluarga) dari ibu¹³. Keturunan dan warisan tidak
ditentukan tanpa syarat oleh garis ayah; anak-anak tidak secara otomatis
menjadi bagian dari kelompok kerabat ayah; warisan diwariskan melalui pihak
ibu. Laki-laki sering pindah ke kelompok istri mereka. Situasi ini jauh dari
tatanan patriarki murni. Pendaftaran resmi dan catatan pajak secara paksa
mengakhiri ini.
Pernyataan tersebut—oleh seorang pejabat yang bekerja selama bertahun-tahun di Ceram, di wilayah yang berbatasan dengan distrik komandan bivak Honitetoe —hampir sama persis dengan pernyataan yang dibuat oleh De Vries. Oleh karena itu, tidak dapat diterima untuk mengabaikan keakuratan data ini dengan merujuk pada literatur sebelumnya. Sebaiknya kita setuju dengan apa yang dikatakan De Vries sendiri di halaman 127 bukunya: bahwa rincian yang ia berikan hanya memberikan gambaran umum tentang sistem hukum keluarga yang kompleks, dan bahwa hanya studi menyeluruh yang dapat menghasilkan pemahaman yang lengkap.
Perbedaan mencolok dalam banyak hal antara dua kelompok penduduk utama di Seram Barat— Wemale dan Alune—terutama menarik perhatian mereka yang telah lama berhubungan dengan penduduk pedalaman. Di antara penduduk pesisir, perbedaan ini telah kabur karena berbagai pengaruh yang merata; setidaknya, perbedaan tersebut tidak begitu jelas di sana seperti di antara suku-suku pegunungan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa De Vries memilih pembagian ini sebagai dasar deskripsinya, dan juga dapat dipahami bahwa ia mencoba menyusun ikhtisar mengenai ciri-ciri pembeda yang paling menonjol di antara kedua kelompok tersebut. Sebagian data baru telah dimasukkan ke dalam ikhtisar ini, dan wajar saja jika Dr. Duyvendak —yang mempertanyakan keakuratan data ini—tidak setuju dengan ringkasan tersebut.
Sekarang, daftar ini tentu dapat disempurnakan seandainya De Vries juga mampu mengenal pusat wilayah Alune yang sebenarnya, selain beberapa desa Alune di distriknya sendiri. Dengan demikian, kemungkinan bahwa daftar tersebut memerlukan penambahan dan revisi sama sekali tidak dikecualikan; misalnya, perbedaan mencolok dalam struktur rumah antara kedua kelompok dapat disertakan.
Namun, ini relatif kecil.
Hal yang penting adalah bahwa gambaran umum seperti ini memang berharga—terutama bagi mereka yang bertugas di Seram atau yang akan bertugas di sana, karena gambaran umum ini memungkinkan mereka untuk lebih cepat mengorientasikan diri di lingkungan yang belum dikenal dan memahami ciri-ciri khas penduduk. Uraian di atas diharapkan dapat memberikan sedikit kontribusi untuk menjelaskan beberapa lembaga suku pegunungan di Seram Barat, dan sekaligus sekali lagi menyoroti perlunya studi etnografi tambahan di wilayah ini dalam waktu dekat.
Saya juga yakin telah menunjukkan bahwa catatan De Vries layak mendapat pengakuan lebih dari yang Dr. Duyvendak bersedia berikan—bahwa catatan itu penting bagi siapa pun yang ingin memahami populasi di pedalaman Seram Barat, dan bahwa catatan itu dapat sangat berguna bagi mereka yang harus berinteraksi dengan orang-orang tersebut.
==== selesai ====
Catatan kaki
1. Penelitian yang dirangkum dalam Seran ( Mededeling Encycl. Bureau), Batavia 1923, diselesaikan pada tahun 1918 untuk Seram Barat.
2. Mungkin ada baiknya untuk dicatat di sini bahwa pernyataan saya sendiri sebagian besar didasarkan pada pengalaman dan pengamatan selama dua periode ketika saya bertanggung jawab atas administrasi sipil dan militer di Seram Barat (1905–1907 dan 1916–1919). Jabatan saya sebagai arsiparis Institut Moluccan dalam beberapa tahun terakhir telah memungkinkan saya untuk tetap mendapatkan informasi tentang literatur dan perkembangan di Seram.
3. Esai oleh Letnan Giel tentang pedalaman Seram Barat dan penduduknya tidak termasuk dalam daftar ini, meskipun Dr. Duyvendak, seperti yang ditunjukkan dalam catatan kaki di halaman 20 bukunya, mengetahuinya.
4. Laporan Vergadering van het Indisch Genootschap pada tanggal 23 Oktober 1916.
5. Lihat Seran (Med. Enc. Bur.), hal. 109; dan Dr. E. Stresemann, “Religiöse Gebräuche auf Seran” dalam Tijdschrift Bataviaasch Genootschap , LXII, 1923, hal. 339.
6. Ketika mempertimbangkan pernyataan berikut, perlu diingat bahwa pada saat penyelidikan saya, belum ada loema-inai baru yang dibangun.
7. Dapat dinyatakan dengan kepastian yang cukup bahwa kata soa dalam ranah hukum (dan bahasa) masyarakat Ambon di Maluku bukanlah kata asli, tetapi khusus untuk masyarakat Ternate. (Lihat pembahasan ini oleh FD Holleman dalam Het adatgrondenrecht van Ambon en de Oeliasers, hal. 8.)
8. Anggapan bahwa soa berasal dari kata Wemale soane untuk baileo (De Vries, hlm. 132) menurut saya tidak benar.
9. Kemungkinan besar daftar seperti itu sudah ada di Ceram.
10. Rincian ini dibagikan kepada saya oleh Letnan Satu DD Vodegel, yang bertugas selama 4½ tahun sebagai komandan bivak di Honitetoe setelah De Vries.
11. Hal ini telah terlihat jelas selama penyelidikan beberapa kasus Alfur sebelum tahun 1919. Lihat juga pernyataan Giel mengenai masalah ini.
12. Tijdschrift van het Koninklijk Ned. Aardr. Genootschap, XLII, 1925, hlm.696–697.
13. Nama loema -inai ?
Catatan Tambahan
a. Mensch en Maatschappij volume 4, seri/nomor 4 (1928)
b. Johan Philip Duyvendak
c. Tinjauan atau Riview dari J.Ph. Duyvendak mengenai buku G. De Vries, ada pada halaman 537-538 di volume 4, seri/nomor 4, tahun 1928 (lihat catatan tambahan huruf a)
d. Gijsbertertus de Vries. lahir di Gombong, Jawa Timur, pada 5 September 1888, dan meninggal pada tahun 1970. Putra dari Bram de Vries dan Rosalia Adolfina Brouwer. Ia menikah dengan Johanna Cornelia de Hammer pada tahun 1916.
e. Buku karya G. De Vries Bij de Berg-Aifoeren op West-Seran. Zeden, gewoonten en mythologie van een oervolk, diterbitkan di Zutphen oleh penerbit W.J. Thieme & Cie, tahun 1927
f. Kami belum menemukan periode pasti G. De Vries menjadi Komandan Bivak di Honitetu, namun pastinya sebelum tahun 1927, jadi mungkin ia menjadi komandan sekitar 1921 – 1923
g. W. Ruinen, Gezaghebber van de onderafdeeling West-Ceram (2 Maret 1905-1907, dan 2 Agustus 1916-1919). Pada periode pertama (1905-1907) ia menggantikan F.J.P. Sachse (1904-1905) dan periode kedua ia juga menggantikan F.J.P. Sachse (Agustus 1915 – Agustus 1916).
h. Yang dimaksud dengan karya Frans Jonathan Pieter Sachse adalah,
§ F.J.P. Sachse, 'Iets over staatsexploitaitie van Seran', TBB 28 (1905) 533-544.
§ Sachse, F.J.P., Het eiland Seran en zijne bewoners (Leiden 1907).
§ Sachse, F.J.P., Gegevens uit de nota betreffende de onderaf deeling West-Ceram Encyclopaedisch Bureau (Batavia 1919). Voor den dienst.
§ Sachse, F.J.P., 'Ontwikkelingsmogelijkheden van het eiland Ceram', TAG 3e s. 37 (1920) 379-382.
§ Sachse, F.J.P., Seran MEB 29 (Weltevreden 1922).
i. Yang dimaksud dengan karya Odo Deodatus Tauern adalah Patasiwa und Patalima; vom Molukkeneiland Seran und seinen Bewohnern (Leipzig 1918)
j. Prof Nieuwenhuijs yang dimaksud bernama Anton Willem Niuwenhuijs (1864 – 1953)
k. Prof. Cornelis van Volenhoven (1874 – 1933)
l. Prof Dr Johan Karl Ludwig Martin (1851 – 1942). Ia berkunjung ke Seram dalam tahun 1892.
m. J. van Hecht Muntingh Napjus adalah assisten-resident van de afdeeling Seram (15 Juni 1909 – 26 Juni 1911), menggantikan M.C. Schadee (April 1907 – Juni 1909)
n. Prof Dr. Karl Deninger (1878 – 1917) melakukan perjalanan ke Maluku, Buru dan Ceram pada tahun 1906-1907, juga pada tahun 1910 - 1912
o. Dr. Erwin Stresemann (1889 – 1972)
p. Willem Henri Frederik Giel (Surabaya, 14 Desember 1884 – Kalidjati, 25 Januari 1923), seorang penerbang, putra dari Willem Johannes Giel (1859-1945) dan Anna Sophia Louiza Margaretha Weiffenbach (1864-1923), menikah dengan Adriana Louise Clignett (1885 – 1961) pada 3 September 1907 di Den Haag. Ia pernah bertugas di Piru, Seram
q. Aanteekeningen over Het Kakhianverbond op West-Ceram, Ambon 11 Agustus 1916
r. Willem Karel Hendrik Feuilletau de Bruyn (Palembang, 11 Juli 1886 – Den Haag, 13 Mei 1972), putra dari Gaston Feuilletau de Bruyn (Batavia, 5 Mare 1848 – Nijmegen, 26 November 1902) dan Maria Annette Bertha de Klerck (Surakarta, 19 Mei 1862 – s’Gravenhage, 29 Januari 1927). Menikah dengan Sally Aletta Clara Spiering (?? – 8 September 1914) pada 14 April 1908, dan Henriëtte Emma Mulder (Sukabumi, 25 Maret 1893 -??) pada 16 Desember 1918 di Batavia. Ia bertugas di West Ceram pada periode 1908-1910 sebagai anggota ekspedisi militer pada tahun itu
s. Letnan A.M. Sierevelt menjadi komandan bivak di Riring pada tahun 1915 – 1919
t. Laporan serah terima itu “berjudul” De Onder-afdeeling Amahei (Seran), juga dimuat pada Tijdschrift van Het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, deerde serie, deel 42, 1925, halaman 653-724
u. Gerard Louwrens Tichelman (Palembang, 31 Januari 1893 – Haarlem, 3 Januari 1962), putra dari Johanes Cornelis Tichelman (3 Juni 1859 – 28 Maret 1901) dan Christina Louwrina Albertina van Eijck (28 Mei 1868 – 31 Januari 1938). Menikah dengan Sjoukjen Margaretha Elisabeth Albertina Posthuma (28 Agustus 1892 – 10 Agustus 1944) di Ambon pada 27 Desember 1917. G.L. Tichelman menjadi Gezaghebber onderafdeeling Amahei pada Januari 1918 – November 1922.


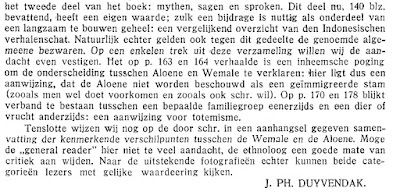








Tidak ada komentar:
Posting Komentar