(bag 2)
[Timo Kaartinen]
Kerjasama dan Perdagangan
Kedudukan khusus masyarakat Banda setelah kolonisasi Maluku membuat dapat dipahami bahwa mereka menolak untuk menyebut diri mereka sebagai orang yang diasingkan atau orang buangan, bahkan jika pengamat Belanda menggunakan bahasa seperti itu untuk mencatat keberadaan mereka di Seram Timur dan Kepulauan Kei. Daerah-daerah ini tidak pernah dikontrol secara efektif oleh VOC, dan Kepulauan Kei hampir tidak pernah dikunjungi oleh pejabat atau pedagang Belanda sampai akhir abad ke-19. Ini adalah awal dari “zaman kolonial baru”75 dimana pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk memerintah, memberlakukan pajak, dan mengembangkan seluruh populasi di wilayahnya. Di Kepulauan Kei, periode antara 1860 dan 1880 sangat menarik untuk mengamati dinamika antara elemen kekaisaran perdagangan yang lebih tua dan terhubung secara longgar dengan kekuatan negara modern.
Perubahan ini tidak boleh dilihat sebagai representasi transisi sejarah yang jelas. Dalam pembahasan tentang oposisi Deleuze dan Guattari antara mesin perang dan negara, Bruce Kapferer76 berargumen bahwa kedua objek tersebut tidak boleh dilihat sebagai catatan total masyarakat aktual, tetapi sebagai modalitas pembentukan atau perakitan kekuasaan. Seperti yang telah saya kemukakan, pengasingan memiliki lebih dari satu strategi yang digunakan VOC untuk menstabilkan kendali teritorialnya. Pengasingan kembali muncul dalam imajinasi sejarah Belanda sebagai hal perpindahan jauh dari “rumah” dan masuk ke ruang kolonial. Dalam imajinasi masyarakat Banda, ruang antar pulau penuh dengan lintasan ke rumah lain, atau tempat dimana seseorang dianggap sebagai kerabat. Di sisa pembahasan ini, saya menyatakan bahwa pengasingan memiliki efek ideologis yang menstabilkan untuk 2 mode teritorial yaitu : pejabat pemerintah dan pelancong-pelancong pribumi.
Dalam sebuah laporan yang ditulis setelah kunjungannya ke Kepulauan Kei pada tahun 1887, Baron van Hoëvella, seorang penganjur utama studi hukum adat/pribumi, mengomentari kurangnya tradisi naratif tentang keadaan dimana kedua desa berbahasa Banda itu. Menurut Baron van Hoëvell, “mereka tahu bahwa mereka berasal dari sana [Banda], tetapi cerita tentang alasan pengusiran mereka tidak lagi eksis”77.
Baron van Hoëvell jelas mengharapkan untuk menemukan narasi yang sesuai dengan pengertian teritorialnya tentang daerah tersebut di bawah negara kolonial Belanda. Pengamat Belanda abad ke-19 seperti dia adalah seorang romantis yang ingin menemukan jejak sejarah mereka sendiri, yang didokumentasikan secara intensif selama tahun 1880-an, dari tempat-tempat terpencil seperti Kei. Sekitar waktu yang sama, Johann Riedel78/b menyebutkan bahwa Eli dan Elat “didiami oleh orang-orang yang melarikan diri dari Banda pada tahun 1621”. Namun, dalam narasi Belanda abad ke-18, orang Banda yang memberontak melarikan diri ke Rarakit, sarang bajak laut di Seram Timur, “dimana, atau di sekitarnya, mereka sebagian besar bertahan setelah melarikan diri”79.
Orang Banda yang bermigrasi ke timur Maluku sulit untuk ditentukan karena mereka tidak membentuk komunitas yang berlainan. Tantangan politik mereka terhadap pemerintahan Belanda tidak terdiri dari perlawanan teritorial. Alih-alih, orang Banda bertahan berkat sebuah sistem yang dikenal di Maluku dan Papua yaitu sosolot, “waralaba perdagangan” lokal yang dipimpin oleh perantara yang merupakan bagian dari komunitas pedagang regional80. Tampaknya sistem ini juga memfasilitasi penyelesaian penduduk Banda di Kepulauan Kei. Hingga tahun 1960-an, orang-orang Banda Eli menjalankan hak perdagangan di antara sekutu lama mereka di pesisir Papua.
Hingga akhir abad ke-19, perhatian utama VOC di Maluku adalah monopoli rempah-rempahnya. Pada akhir abad ke-19, pandangan kolonial beralih ke masalah mengatur penduduk pribumi. Ketertarikan pada peristiwa-peristiwa kolonial awal di antara para sejarahwan yang menulis pada tahun 1880-an mencerminkan sentimen kekaisaran saat itu, tetapi juga merupakan upaya untuk menemukan preseden bagi munculnya geografi kekuasaan. Baron van Hoëvell mencari dengan sia-sia geografi mitos orang Banda karena hal itu diungkapkan dalam lagu-lagu naratif tentang pelayaran laut para figur-figur leluhur. Tujuan mereka meliputi Mekkah, Ambon, Banda, dan sejumlah pulau antara Maluku Tengah dan Kepulauan Kei. Saya berpendapat pada kajian lain81 bahwa lagu-lagu ini adalah bagian dari kompleks yang lebih besar dari motivasi budaya yang berkaitan dengan perjalanan lalu lintas : mereka mendorong para pemuda untuk mencari kekayaan dan pengetahuan diri dengan mengunjungi tempat-tempat lain. Saat ini orang Banda masih menganggap pengalaman perjalanan melintasi laut sebagai bagian dari inisiasi laki-laki menuju status dewasa penuh : laki-laki yang berbicara dalam pertemuan publik diharapkan memiliki pengalaman dari pekerjaan hibah di tempat lain.
Lagu-lagu tersebut mempertahankan pandangan orang Banda sebagai jaringan sosial daripada kelompok lokal. Mereka menggarisbawahi bahwa orang Banda adalah orang asing dalam masyarakatKepulauan Kei. Mitologi orang Kei berkisar pada orang asing yang berkuasa – laki-laki atau wanita – yang memberi pengetahuan memasak, pertukaran pernikahan, dan otoritas politik kepada orang pribumi. Masyarakat Banda Eli mengklaim bahwa seluruh desa mereka terdiri dari orang-orang asing, yang sangat terhubung dengan jaringan perdagangan antar pulau yang menghubungkan Kei dengan tempat lain. Sedangkan status kelompok utama lainnya di Kei didasarkan pada kemampuan mereka untuk mengontrol pertukaran reproduksi dan peredaran benda-benda berharga dalam masyarakat, orang Banda menghindari perkawinan dengan orang Kei. Perkawinan di Kei mengikat orang ke dalam hierarki domestik dan hubungan pertukaran jangka panjang. Itu menciptakan apa yang oleh Kei sebut sebagai inan lifan, hutang seumur hidup kepada mertua dan leluhur yang dikuburkan di tanah Kei. Orang Banda, di sisi lain, membayangkan nenek moyang mereka hadir di tempat-tempat jauh yang hanya diakses oleh pelancong individu. Kekerabatan mereka tidak terbatas pada hubungan sosial yang terlokalisir tetapi mengalir82 menuju dunia perdagangan antar pulau.
Perspektif kosmologis ini menjungkirbalikkan politik pengasingan. Saya berpendapat bahwa kolonialis Belanda menggunakan pengasingan sebagai sarana untuk mengubah orang menjadi subyek kolonial yang akan mengisi dan memperluas ruang di bawah kendali mereka. Pengasingan mencabut orang-orang ini dari kondisi sosial dan politik yang mereka inginkan. Di tempat pengasingan mereka, mereka diharapkan mempelajari hasrat baru dan tunduk pada klasifikasi sosial yang baru, seperti konstruksi etnis kolonial. Namun, orang-orang Banda lolos dari proyek teritorialisasi ini. Di Maluku Tengah dan Sulawesi, mereka dengan senang hati melebur ke dalam kategori etnis yang lebih besar dan tatanan politik yang menentang Belanda. Pada saat yang sama, khususnya di Kei, mereka tetap menjadi orang asing di tempat tinggal mereka.
Perhatian sejarah lisan Van Hoëvell tidak murni bersifat akademis. Sebagai pendukung politik etis Belanda, ia ingin mendefinisikan kelompok-kelompok dengan identitas budaya yang stabil dan mengembangkan institusi hukum mereka. Negara kolonial dapat memperluas tatanan hukumnya ke daerah-daerah terpencil hanya dengan menciptakan sistem hukum adat. Paradoksnya, orang Banda menghalangi proyek ini karena mereka telah mengambil peran ahli hukum di antara tuan rumah orang Kei. Kehadiran yang tidak nyaman dari orang Banda dan orang luar lainnya adalah alasan pengasingan hukuman pada abad ke-19, yang akan dibahasa selanjutnya.
Pengasingan Iman Budiman
Pada tahun 1860-an, pemerintah Belanda mulai memperluas kehadirannya ke daerah-daerah dimana penduduk Maluku secara efektif memerintah diri mereka sendiri. salah satunya adalah Kepulauan Kei, sebuah kepulauan yang terletak di sebelah barat Aru dan sekitar 100 km dari pantai Papua Nuigini. Karena “sifat penduduk pribumi yang haus darah”, seperti yang dikatakan oleh Robert Townsend Farquhar83, para pedagang bebas Banda menghindari mengunjungi pulau-pulau tersebut. Meski begitu, orang Banda bergantung pada wilayah yang lebih jauh ke timur untuk persediaan makanannya, dan pedagang pribumi dari Kei Besar berlayar ke Banda setiap tahun dengan perahu mereka sendiri, membawa minyak, sagu, kelapa, dan periuk tanah84. Ekspor periuk tanah adalah bukti bahwa Banda Eli memiliki peran besar dalam perdagangan ini : pembuatan periuk di Kei Besar hanya terbatas di desa ini.
Dapat dikatakan bahwa orang Banda yang tinggal di Kei mengetahui peristiwa yang mengubah koloni VOC menjadi negara kolonial modern. Indonesia timur berada di tangan Inggris selama 2 periode pendek selama dan setelah Perang Napoleon, dan VOC menyatakan bangkrut pada tahun 1799. Ketika kekuasaan Belanda di Ambon dipulihkan pada tahun 1817, orang-orang di Ambon memberontak terhadap kebijakan baru yang menekan perdagangan cengkih pribumi85. Hanya di tempat-tempat yang jauh, seperti Aru dan Kepulauan Barat Daya, Belanda dapat berpura-pura meneruskan kehadiran kolonial yang dimulai oleh VOC. Ketika Kapten Belanda, Dirk Hendrik Kolffc, berlayar di sekitar Maluku Tenggara dengan kapal perang, ia memusatkan perhatian pada daerah-daerah tersebut dan melewati, tetapi tidak berhenti di Banda Eli – meskipun ia mencatat bahwa itu dianggap sebagai tempat terpenting di Kei86.
Laporan Belanda dari setengah abad kemudian menyajikan gambaran yang sangat berbeda dari wilayah yang sama. Pada tahun 1862, seorang pejabat Belanda bernama H.C. Eijbergend melakukan pemeriksaan menyeluruh di Kei Besar bagian utara, dengan perintah untuk “mengakhiri pelanggaran hukum dan ketidakteraturan yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir”87. Perhatian pemerintah terhadap hukum dan ketertiban akan didasarkan pada laporan para pedagang dan penduduk desa yang terkena dampak karena tidak ada kunjungan Belanda ke daerah itu selama lebih dari 1 dasawarsa88. Penduduk setempat tidak mengetahui adanya kapal Belanda yang berkunjung pada tahun 1850; mereka hanya ingat bahwa 2 kapal telah singgah di desa terdekat sekitar 30 tahun sebelumnya – sebuah kunjungan yang Eijbergen catat dilakukan pada tahun 183389.
Pada pertengahan abad ke-19, kepentingan komersial yang meningkat di hutan-hutan kepulauan Kei menghasilkan konflik sumber daya, dan orang Banda mengambil peran sebagai mediator terhadap tetangga orang Kei mereka90. Intervensi hukum tradisional mereka jelas merupakan gangguan bagi pedagang luar, yang meminta bantuan pemerintah Belanda. Pada perjalanan pertamanya, Eijbergen memihak Ismael, sekutu orang Banda, yang memberitahnya secara rahasia bahwa Budiman, Imam Banda Eli, menuntut agar ia membayar denda tahunan karena kawin lari dengan seorang budak dari keluarga Imam.
Eijbergen kembali mengunjungi Kepulauan Kei pada tahun 1864. Dalam perjalanan ini, ia mulai lebih memperhatikan orang-orang yang menurut pandangannya tinggal di tempat yang salah. Orang pertama yang dibawanya adalah Abdullah, seorang laki-laki yang memperkenalkan dirinya sebagai Imam Kataloka, sebuah pulau di dekat pantai timur pulau Seram. Abdullah pernah tinggal di Aru sebagai pengajar di rumah anak-anak lelaki orang Bugis selama 4 tahun. Kemudian dia kawin lari dengan istri tuan rumahnya yang merupakan orang Bugis91. Eijbergen memberitahu Abdullah bahwa dia tidak berhak tinggal di Aru dan menempatkannya di kapalnya, untuk dibawa ke tahanan gubernemen di Banda, dimana dia akan dipulangkan ke Kataloka92.
Sebagai seorang Muslim dari Seram Timur, Abdullah adalah bagian dari diaspora perdagangan Islam yang sama yang dicurigai Eijbergen menimbulkan kerusuhan di tempat lain yang dia kunjungi93. Eijbergen sudah curiga terhadap orang-orang seperti itu setelah mendengar pengaduan terhadap Imam Budiman 2 tahun sebelumnya94. Ketika dia sampai di Kei Besar dalam perjalanan keduanya, Budiman datang menemuinya dengan rombongan besar dan duduk sambil merokok cerutu95. Menyembunyikan kekesalannya, Eijbergen pergi ke desa lain, dimana dia telah memanggil semua kepala dari utara Kei Besar. Budiman telah meyakinkan Eijbergen bahwa dia telah mengirimkan kabar kepada para pemimpin yang berselisih dengannya, tetapi ketika mereka tidak muncul dalam pertemuan tersebut, Eijbergen memutuskan untuk menangkap Budiman96. Dia mengirim Imam ke kapalnya dibawah pengawalan 2 serdadu dalam perintah membuat sidang terpisah kepada pimpin Banda Eli lainnya. Mereka mengungkapkan bahwa Budiman telah mengenakan denda besar pada seorang pemimpin yang mempermasalahkan hak atas tanahnya dan menyerang desanya ketika semua tidak dibayar97.
Penangkapan Budiman menandai titik balik dalam hubungan antara Kepulauan Kei dan Negara Kolonial. Dalam kunjungan Eijbergen, Banda Eli dan komunitas pedagang Muslim lainnya tidak melawan otoritas negara tetapi mengambil alihnya dengan menjadika bendera Belanda dan lambang pemerintah lainnya sebagai tanda kekuasaan mereka sendiri. Segera Belanda mengirim hongi – sebuah armada kano perang yang meniru ekspedisi penghukuman VOC – untuk menghukum desa para pembunuh yang diduga menjadi penyihir98. Untuk membatasi kegiatan semacam itu, Belanda mendirikan sebuah pos pemerintahan di Kepulauan Kei pada tahun 1882.
Tidak ada informasi tentang Budiman setelah diasingkan dari Kei. Kerabat Budiman, bagaimanapun, telah menjaga ingatannya tetap hidup. Kedua putranya bertugas sebagai Imam di masjid-masjid Banda Eli yang berbeda. Wahab, si sulung, menjadi Imam masjid jumatan yang bergengsi, sedangkan si bungsu, Ismail, menjadi Imam mesjid di Futelu, ujung selatan desa. Selama saya bekerja pada tahun 1994-1996, Imam masjid jumatan adalah Haji Jeilani Salamun, keturunan langsung Budiman dari garis laki-laki99.
Cerita Haji Jeilani tidak memberikan banyak detail tentang keadaan pengasingan Budiman. Alih-alih menyatakan bahwa Budiman menentang kekuasaan Belanda, Jeilani menekankan keyakinannya bahwa Budiman tidak memiliki hubungan langsung dengannya. Menurut sebuah cerita yang diulang-ulang oleh Jeilani kepada saya, dia pernah bertemu dengan seseorang yang tampak sangat akrab dari kota Semarang di Jawa Tengah saat berkunjung ke Ambon. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia adalah keturunan seorang pria yang pindah ke sana dari Banda Eli. Jeilani yakin bahwa orang itu memang kerabat Budiman, cicit lain dari Budiman 100.
Cerita Jeilani mengikuti alur yang mirip dengan lagu-lagu daerah Banda Eli. Pertemuan yang paling mendalam dan mengungkapkan diri dengan kerabat terjadi di tempat yang jauh, dimana orang tidak pernah mengharapkan orang asing untuk menunjukkan kasih sayang dan kebaikan yang serupa dengan apa yang diterima dari kerabat. Kasus ini, serta mitos tokoh-tokoh leluhur yang diasingkan, menunjukkan kekerabatan secara ekspansif, sebagai sumber identitas dan pembedaan pribadi.
Saya telah menyatakan bahwa para pejabat Belanda tertarik untuk menstabilkan lembaga-lembaga budaya yang berdiri untuk tatanan hukum dan membantu mengatur populasi yang beraneka ragam di negara kolonial yang sedang berkembang. Mengangkut orang menjauh dari daerah yang bukan tempatnya sesuai dengan kebijakan ini. Namun, hukuman Budiman lebih mengingatkan pada praktik VOC pada pengasingan “bangsawan”. Tidak tahu harus “mengembalikan” ke mana, para pejabat Belanda memindahkannya ke ruang kolonial, mungkin ke penjara di Ambon atau Jawa.
Clare Anderson dan Carol Liston, masing-masing dalam bab 1 dan 8 pada buku inie, berpendapat bahwa dalam beberapa situasi hukuman pengasingan dapat dianggap memiliki hasil yang menguntungkan, misalnya, ketika menunjuk pada kemungkinan baru akses ke domain kolonial. Meskipun pengasingan Budiman dimaksudkan sebagai tindakan represif politik, hal itu memiliki konsekuensi yang tidak disengaja serupa dengan yang menjadi perhatian pihak berwenang Inggris dalam kasus Maharaj Singh, yang dibahas oleh Anand Yang (bab 3 dalam buku inif). Keluarga Budiman telah mengklaim jabatan kepala desa yang paling berpengaruh di desa itu, dan masih menganggapnya sebagai salah satu nenek moyang yang melakukan perjalanan ke luar negeri yang mendasari hubungan kekerabatan orang Banda dengan tempat-tempat yang jauh. Karena catatan Eijbergen yang diterbitkan tentang penangkapan Budiman, dia mungkin satu-satunya orang Banda abad ke-19 yang menonjol sebagai individu dalam catatan sejarah. Bagi kerabat Budiman, relokasi paksa leluhur mereka memperluas ruang etnis yang mereka bayangkan ke lokasi yang diidentifikasi dengan pendidikan dan kekuasaan birokrasi – dua aspek modernitas Indonesia yang telah berhasil dikejar oleh banyak orang Banda sejak tahun 1960-an dan seterusnya.
Pengasingan dan Pembentukan Ruang Kolonial
Praktik-praktik monopoli dan kekerasan VOC bertentangan dengan kepekaan Belanda kontemporer seperti halnya dengan gagasan penduduk pribumi tentang kekuasaan yang sah di Maluku. Inilah sebabnya mengapa tahap-tahap awal kolonialisasi jauh lebih sedikit kaitannya dengan pembangunan negara daripada kebalikannya : apa yang disebut Deleuze dan Guattari101 sebagai mesin perang. Sulit untuk tidak melihat armada hongi VOC sebagai organisasi “suku”, yang hampir secara spontan berkumpul untuk menyerang “suku-suku” tetangga yang jaraknya beberapa ratus kilometer.
Pengasingan “bangsawan” adalah cara yang jelas untuk merampas ketertiban masyarakat adat dan mengubahnya menjadi mesin perang. François Valentyn dan penulis kontemporer lainnya hampir tidak pernah memperhatikan hal ini karena komitmen mereka terhadap legitimasi VOC yang mirip suatu negara. Tulisan-tulisan kolonial menolak untuk melihat pembantaian dan perampasan penduduk pribumi sebagai peristiwa kontingen dan tragis dan menampilkannya sebagai hasil dari keputusan dan kebijakan yang disengaja. Depopulasi Hoamoal dan penaklukan Banda direpresentasikan sebagai tindakan berdaulat yang memulihkan, bukan menggantikan, tatanan politik dan hukum yang ada. Namun, pengasingan “bangsawan” merupakan ambiguitas narasi yang berorientasi pada negara ini. Bahkan jika pengasingan kadang-kadang berpakaian sebagai cara yang baik untuk menanamkan tata negara modern pada bangsawan pribumi, hal itu menghadapkan mereka dengan kekuasaan kolonial yang memaksa dan menghukum – sesuatu yang diharapkan akan diinternalisasi dan diterapkan oleh hukuman pengasingan. Pengasingan Sultan Hamzah ke Manila, misalnya, membiasakannya dengan monarki absolut yang dicontohkan oleh Philip II, tetapi menghilangkan kepekaannya terhadap cara otoritas yang sah dipahami di antara rakyatnya di Maluku. Dalam kasusnya, pengasingan menciptakan kekosongan kekuasaan negara yang tidak terduka di dekat pangkalan VOC di Ambon, memaksa kompeni melakukan tindakan militer yang menyusahkan yang mungkin ingin dihindarinya.
 |
| Masyarakat Banda Eli |
Apa yang saya sebut ruang kolonial diciptakan oleh peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Ruang tidak boleh dipahami dengan wilayah, distribusi geografis dari bentuk dan relasi sosial tertentu. Penaklukan VOC atas Banda dan Hoamoal menggusur penduduknya dan mengubah banyak dari mereka menjadi budak dan serdadu. Ruang kolonial di Maluku Tengah muncul dari peristiwa deteritorialisasi tersebut. Ruang ini bukan sekedar mitra “modern” dari negara-negara pribumi di wilayah pengaruh VOC. Kita mungkin menyebutnya sebagai ruang “haeccic”102 karena tidak menarik banyak orang dengan menawarkan mereka cakrawala ideologis dan identitas alternatif, tetapi hanya dengan merampas rumah, status pribadi, dan hubungan mereka sebelumnya.
Kualitas ruang kolonial ini dapat menjelaskan banyak hasil tidak terduga dari pengasingan orang terjajah, serta fakta bahwa pengasingan sering dikaitkan dengan kemungkinan ekonomi, budaya, dan politik baru. Kemampuan pedagang pribumi untuk menantang monopoli VOC didasarkan pada pola sejarah sebelumnya, tetapi migrasi orang Banda ke Seram Timur dan Kei juga menciptakan hubungan baru antara tempat perdagangan lokal dan pasar di seluruh dunia. Teritorialitas baru orang Banda menempatkan mereka pada posisi kekuasaan relatif terhadap masyarakat yang lebih menetap : melalui aktivitas komersial mereka, mereka berpartisipasi dalam sistem yang diciptakan oleh Belanda. Pada saat yang sama, mereka sadar bahwa keterlibatan penuh dalam sistem kolonial akan mencabut mereka dari etnis khusus yang terdeteritorialisasi yang mereka nyatakan sebagai kekerabatan dengan kerabat jauh. Upaya Belanda untuk menempatkan mereka pada akhir abad ke-19 tidak menghapus rasa kekeluargaan mereka dengan tempat lain : secara paradoks, penangkapan dan pengasingan Imam Budiman menghubungkan keluarganya dengan tempat lain yang jauh dimana mereka berharap akan merasa diterima.
Fakta bahwa perkembangan ruang kolonial tidak mengikuti logika sejarah yang dapat diprediksi juga berarti bahwa kualitas dan makna pengasingan terus bergeser sepanjang masa kolonial. Dalam konteks yang dibahas dalam kajian ini, praktik kolonial pengasingan bergeser antara rezim afirmatif dan rezim hukuman. Pengasingan digunakan untuk mengubah otoritas politik pribumi tetapi juga untuk menunjukkan kekuatan luar biasa VOC terhadap orang-orang yang memegangnya. Pada akhir abad ke-19, pengasingan telah menjadi usang sebagai alat untuk mengelola negara-negara pribumi, tetapi ia muncul kembali sebagai tokoh sentral imajinasi sejarah, didorong oleh kebanggaan tentang Kerajaan Belanda, rasa bersalah tentang masa lalunya yang penuh kekerasan, dan kebutuhan untuk menggantikan populasi kolonial di peta.
Tidak jelas apakah kata melayu yaitu kata asing (alien) memiliki konotasi yang sama dengan kata pengasingan (exile) sebelum terbentuknya batas-batas negara Indonesia. Negara Kolonial selalu mampu mengusir orang, tetapi rakyatnya menciptakan identitas baru yang bermakna secara sosial bagi mereka yang tiba di tempat baru. Praktik memori orang Banda luar biasa karena kekuatan mereka untuk mengubah efek pengasingan dan depersonalisasi dari perpindahan menjadi kebalikannya : keintiman yang aneh dengan kerabat leluhur dan tanah air dengan figur kekuatan agama dan politik.
========= selesai =======
Catatan Kaki
75. M. C. A. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, c. 1300 to the Present, 2nd ed. (London: MacMillan Press, 1993), 151.
76. Bruce Kapferer, Te Feast of the Sorcerer: Practices of Consciousness and Power (Chicago: University of Chicago Press, 1997), 284.
77. C. W. W. C. van Hoëvell, “De Kei- eilanden,” Tijdschrift voor Indische Taal- , Land- en Volkenkunde 33 (1890): 158.
78. J. G. F. Riedel, De sluik- en kroesharige rassen tusschen Selebes en Papua (Te Hague: Martinus Nijhoff, 1888), 217.
79. Valentyn, Beschryvinge van Amboina, 57.
80. Ibid., 126; Tomas Goodman, “The Sosolot: An Eigh teenth Century East Indonesian Trade Network” (PhD diss., University of Hawai‘i, 2006).
81. Timo Kaartinen, “How a Travelling Society Totalizes Itself: Hybrid Polities and Values in Eastern Indonesia,” Anthropological Teory 14, no. 2 (2014): 241.
82. Deleuze and Guattari, A Tousand Plateaus, 216.
83. W. G. Miller, “An Account of Trade Patterns in the Banda Sea in 1797, from an Unpublished Manuscript in the India Office Library,” Indonesia Circle 23 (1980): 50.
84. Ibid., 52.
85. Richard Chauvel, Nationalists, Soldiers, and Separatists: The Ambonese Islands from Colonialism to Revolt, 1880–1950, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 143 (Leiden: KITLV Press, 1990), 21–22.
86. Dirk Hendrik Kolff, Voyages of the Dutch Brig of War Dourga through the Southern and Little- Known Parts of the Moluccan Archipelago and the Previously Unknown Southern Coast of New Guinea Performed during the Years 1825 & 1826 (London: James Madden & Co., 1840), 344.
87. H. C. Eijbergen, “Verslag eener reis naar de Aroe- en Key- Eilanden,” Tijdschrift voor Taal- , Land- en Volkenkunde 15 (1866): 252.
88. Ibid., 338.
89. Ibid., 253.
90. Ibid., 256.
91. Ibid., 305.
92. Ibid., 307.
93. Ibid., 320, 324, 326.
94. Ibid., 336.
95. Ibid., 338.
96. Ibid., 341.
97. Ibid., 344.
98. Ibid., 340.
99. Jeilani’s father, Muhammad, was Budiman’s great- grand son through Budiman’s son Wahab.
100. Kaartinen, Songs of Travel, 174.
101. Deleuze and Guattari, A Tousand Plateaus, 354.
102. Ibid., 261.
Catatan Tambahan
- Baron van Hoevell memiliki nama lengkap Gerrit Willem Wolter Carel Baron van Hoevell, lahir pada 19 Juni 1848 dan meninggal pada 21 Desember 1920. Ia pernah menjadi Controleur van Hila (1871 – 1872), Controleur van Saparua (1872 – 1875), Assisten Resident van Gorontalo (1886-1891), Resident van Ambon (1891 – 1896), Resident van Lampung (1897-1897) dan Gouverneur van Celebes (1898 – 1903)
- Johan Riedel memiliki nama lengkap Johann Gerhard Friedrich Riedel, lahir pada 17 Februari 1832 dan meninggal pada 15 Desember 1911. Ia pernah menjadi Resident van Ambon (1880 – 1883)
- Dirk Hendrik Kolff, lahir pada 14 Februari 1800 dan meninggal pada 15 Desember 1843. Ia menjadi komandan kapal perang Dourga pada tahun 1826.
- H.C. Eijbergen memiliki nama lengkap Hendrik Cornelis Eijbergen, lahir pada 19 November 1819 dan meninggal pada 23 November 1869. Ia pernah menjadi Kepala Sekolah Belanda di Ambon (1843 – 1855). Sejak 1843 – 1868, ia bertugas di Gubernemen Ambon.
- Kajian dari Carol Liston berjudul An Exile’s Lamentations? The Convict Experience in New South Wales, Australia 1788 – 1840 yang ditempatkan pada bab 8, halaman 1993 – 219.
BIBLIOGRAPHY
§ Andaya, Leonard. The
Heritage of Arung Palakka. Leiden:
KITLV Press, 1981.
— — —. The World of Maluku: Eastern
Indonesia in the Modern Period. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 1993.
§ Barnard, Timothy. Multiple Centres of Authority: Society and Environment in Siak and Eastern Sumatra, 1674–1827. Leiden: KITLV Press, 2003.
§ Barraud, Cecile. “Kei Society and the Person: An Approach
through Childbirth and Funerary Rituals.” Ethnos
55, nos. 3–4 (1990): 214–231.
— — —. “Wife- Givers as Ancestors and Ultimate Values in the Kei Islands.” Bijdragen tot de Taal- , Land-en Volkenkunde (1990): 193–225.
§ Chauvel, Richard. Nationalists, Soldiers, and Separatists: The Ambonese Islands from Colonialism to Revolt, 1880–1950. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 143. Leiden: KITLV Press, 1990.
§ Chijs, J. A. van der. De vestiging van het Nederlandsche gezag over de Banda- Eilanden (1599– 1621). Te Hague: Martinus Nijhoff, 1886.
§ Collins, James T. “Language Death in Maluku. The Impact of the VOC.” Bijdragen tot de Taal- , Land- en Volkenkunde 159, nos. 2–3 (2003): 247–289.
§ Collins, James, and Timo Kaartinen. “Preliminary Notes on Bandanese: Language Development and Change in Kei.” Bijdragen tot de Taal- , Land- en Volkenkunde 154, no. 4 (1998): 521–570.
§ Deleuze, Gilles, and Felix Guattari. A Thousand Plateaus: Capitalism & Schizo phre nia. London: Athlone Press, 1988.
§ Eijbergen, H. C. “Verslag eener reis naar de Aroe- en Key- Eilanden.” Tijdschrift voor Taal-, Land- en Volkenkunde 15 (1866): 220–272, 293–361.
§ Ellen, Roy. On the Edge of the Banda Zone: Past and Present in the Social Organi zation of a Moluccan Trading Network. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2003.
§ Friedman, Jonathan. Cultural Identity and Global Pro cess. London: Sage Publications, 1994.
§ Goodman, Tomas. “Te Sosolot: An Eigh teenth Century East Indonesian Trade Network.” PhD diss., University of Hawai‘i, 2006.
§ Gregory, C. A. Savage Money. Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1997.
§ Heeres, J. E. “Dokumenten betreffende de
ontdekkingstochten van Adriaan Doortsman 1645–1646.” Tijdschrift voor de Indische Taal- , Land- en Volkenkunde 6, no. 2 (1896): 246–279, 608–619, 635–662.
— — —. “Eene engelsche lezing ontrent de verovering van Banda en Ambon in 1796
en omtrent den toestand dier eilanden groepen op het eind der achttiende eeuw,
uitgegeven en toegelicht door J. E. H.” Bijdragen tot de Taal-
, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch- Indië 60, nos. 3–4 (1908): 249–368.
§ Hoëvell, C. W. W. C. van. “De Kei- eilanden.” Tijdschrift voor Indische Taal- , Land- en Volkenkunde 33 (1890): 102–159.
§ Jones, Eric. “Fugitive Women: Slavery and Social Change in Early Modern Southeast Asia.” Journal of Southeast Asian Studies 38, no. 2 (2007): 215–245.
§ Kaartinen, Timo. “Handing Down and Writing Down: Metadiscourses
of Tradition among the Bandanese of Eastern Indonesia.” Journal of American Folklore 126 (2013): 385–406.
— — —. “How a Travelling Society Totalizes Itself: Hybrid Polities and Values
in Eastern Indonesia.” Anthropological Theory
14, no. 2 (2014): 231–248.
— — —. “Perceptions of Justice in the Making: Rescaling of Customary Law in
Maluku, Eastern Indonesia.” Asia- Pacifc
Journal of Anthropology 15, no.
4 (2014): 319–338.
— — —. Songs of Travel, Stories of Place:
Poetics of Absence in an Eastern Indonesian Society. Folklore Fellows’ Communications 299. Helsinki: Academia
Scientarium Fennica, 2010.
§ Kapferer, Bruce. The Feast of the Sorcerer: Practices of Consciousness and Power. Chicago: University of Chicago Press, 1997.
§ Knaap, G. J. “A City of Migrants: Kota Ambon at the End of the Seventeenth Century.” Indonesia 51 (1991): 105–128.
— — —. Kruidnagelen en
Christenen. De Verenigde Oost- Indische Compagnie en de bevolking
van Ambon 1956–1696. Verhandelingen
van het Koninklijk Instituut voor Taal- , Landen Volkenkunde 125. Dordrecht:
Foris Publications, 2004.
— — — , ed. Memories van Overgave van
gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw. Te Hague:
Martinus Nijhoff, 1987.
§ Knaap, Gerrit, and Heather Sutherland. Monsoon Traders: Ships, Skippers and Commodities in 18th Century Makassar. Leiden: KITLV Press, 2004.
§ Kolff, Dirk Hendrik. Voyages of the Dutch Brig of War Dourga through the Southern and Little- Known Parts of the Moluccan Archipelago and the Previously Unknown Southern Coast of New Guinea Performed during the Years 1825 & 1826. London: James Madden & Co., 1840.
§ Meilink- Roelofsz, M. A. P. Asian Trade and Eu ro pean Influence in the Indonesian Archipelago. Te Hague: Martinus Nijhoff, 1962.
§ Miller, W. G. “An Account of Trade Patterns in the Banda Sea in 1797, from an Unpublished Manuscript in the India Office Library.” Indonesia Circle 23 (1980): 41–57.
§ Oostindie, Gert, and Bert Paasman. “Dutch Attitudes towards Colonial Empires, Indigenous Cultures, and Slaves.” Eighteenth- Century Studies 31, no. 3 ( 1998): 349–355.
§ Overgekomen Brieven en Papieren in het jaar 1622, tweede boek (boek V), ongefolieerd. Bijlage I t/m IX. Algemeen Rijksarchief. National Archives of the Netherlands, Te Hague, 267–285.
§ Pires, Tome. Suma Oriental: An Account of the East, from the Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512–1515. Vol. 1. Hakluyt Society New Series, vol. 89. London: Hakluyt Society, 1944.
§ Reid, Anthony. “Introduction: Slavery and Bondage in Southeast
Asian History.” In Slavery, Bondage and
De pen dency in South- East Asia, edited by Anthony Reid, 1–43. University of Queensland Press,
1983.
— — —. Southeast Asia in the Age of
Commerce, 1450–1680. Vol. 2, Expansion and Crisis. New Haven, CT: Yale University Press, 1993.
§ Ricklefs, M. C. A History of Modern Indonesia, c. 1300 to the Present. 2nd ed. London: MacMillan Press, 1993.
§ Riedel, J. G. F. De sluik- en kroesharige rassen tusschen Selebes en Papua. Te Hague: Martinus Nijhoff, 1888.
§ Swadling, Pamela. Plumes from Paradise: Trade Cycles in Outer Southeast Asia and Their Impact on New Guinea and Nearby Islands until 1920. Boroko: Papua New Guinea National Museum, in association with Robert Brown & Associates, 1996.
§ Tagliacozzo, Eric. “Smuggling in Southeast Asia: History and Its Contemporary Vectors in an Unbounded Region.” Critical Asian Studies 34, no. 2 (2002): 193–220.
§ Tiele, P. A. Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen
archipel. 2nd ser., vol. 1. Te Hague:
Martinus Nijhoff, 1886.
— — —. Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen
archipel. 2nd ser., vol. 2. Te Hague:
Martinus Nijhoff, 1890.
§ Valentyn, François. Ambonsche zaaken. Vol. 2, pt. 2 of Oud
en nieuw Oost Indiën. Dordrecht: Joannes
van Braam; Amsterdam: Gerard Onder de Linden, 1724.
— — —. Beschryvinge van Amboina. Vol. 2, pt. 1 of Oud
en nieuw Oost- Indiën. Dordrecht:
Joannes van Braam; Amsterdam: Gerard Onder de Linden, 1724.
§ Ward, Kerry. “Blood Ties: Exile, Family, and Inheritance across the Indian Ocean in the Early Nineteenth Century.” Journal of Social History 45, no. 2 (2011): 436–452.
§ Widjojo, Muridan. The Revolt of Prince Nuku: Cross- Cultural Alliance- Making in Maluku, c. 1780–1810. Leiden: Brill, 2009.
§ Winn, Phillip. “Slavery and Cultural Creativity in the Banda Islands.” Journal of Southeast Asian Studies 41, no. 3 (2010): 365–389.
Yang, Anand. “Indian Convict Workers in Southeast Asia in the Late Eigh teenth and Early Nineteenth Centuries.” Journal of World History 14, no. 2 (2003): 179–208.
Zemanek, Karl. “Was Hugo Grotius Really in Favour of the Freedom of the Seas?” Journal of the History of International Law 1 (1999): 48–60.
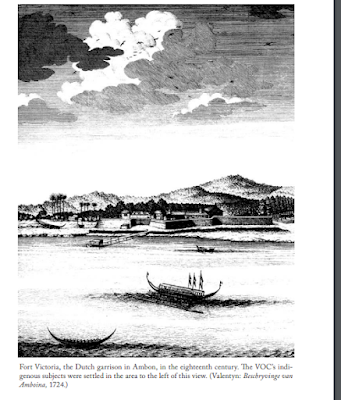

Tidak ada komentar:
Posting Komentar