B. Dualisme di tingkat
regional :
Organisasi Siwa /
Lima sebagai Fakta Politis
Kita
telah melihat bahwa kosmologi yang berpusat pada desa/negeri di Hualu melibatkan
struktur kuadripartit, yang dihasilkan oleh kombinasi oposisi sosial – gender
yang paling umum dengan 2 bentuk dualisme spasial yang berdampingan (bentuk
konsentris dan diametris).
Model
ini, bagaimanapun, hidup berdampingan dengan yang lain yang diwakili oleh Hualu sebagai
bagian dari masyarakat yang lebih besar. Masyarakat yang lebih besar ini
terdiri dari 2 moiety/ kelompok politis, yaitu kelompok “lima” dan “sembilan”,
yang terdapat atau terjadi di sebagaian besar Maluku Tengah, dan di kepulauan
Banda, Kei dan Aru.
Karena
ini adalah sistem regional, kita harus menjelaskannya pada tingkatannya
sendiri, sebelum mempertimbangkan bagaimana hal itu tercermin dalam masayarakat
Hualu, dan
bagaimana hal itu berinteraksi dengan studi struktur kosmologis sejauh ini. Saya
harus menyederhanakan situasi yang sangat rumit ini secara radikal. Memang,
tidak hanya sistem kelompok politik ini
memiliki banyak varian regional : varian ini sendiri tidak dapat dipisahkan
dari sejarah Maluku dalam 5 abad terakhir – sebuah sejarah yang ditandai oleh
interaksi kompleks berbagai budaya dan agama dan oleh perjuangan hegemonik dari
wilayah-wilayah asli (yang “aristokratis” atau “oligarkis” dari Hitu dan Banda,
dan proto-state dari Maluku Utara) serta kekuatan asing, terutama Portugis dan
Belanda.
Namun
sejarah yang rumit ini, yang jelas-jelas tidak dapat digambarkan di sini,
menampilkan sejumlah invarian politik dan terutama ideologis. Ini jelas
menunjukan kesatuan dalam keragaman budaya Maluku, dan mengungkapkan keberadaan
jaringan politik yang luas melalui mana persatuan itu dibawa atau diperkuat. Sebelum
melangkah lebih jauh, izinkan saya memberikan definisi minimal tentang sistem
yang akan saya diskusikan.
Setiap
masyarakat di wilayah tersebut, termasuka dalam kelompok “five” (lima) atau “nine”
(siwa). Setiap masyarakat, kemudian diklasifikasikan dalam konteks regional
dengan merujuk pada numerik/bilangan. Oposisi “lima” dan “sembilan” mungkin
dianggap sebagai bentuk pelabelan yang sepenuhnya berbeda, yang tidak
melibatkan konten spesifik apa pun. Tidak diragukan lagi, ini terjadi dalam
kasus-kasus tertentu namun lebih sering atribut substantif tertentu tersirat
oleh penggunaan label ini. Di sini kita segera menghadapi variasi regional dan
historis, tetapi juga konstan tertentu. Misalnya, setiap indeks numerik
seharusnya mengatur organisasi internal masyarakat ini. Di antara mereka yang
diklasifikasikan sebagai “lima” semuanya harus terjadi dalam unit limaan, dan
di antara anggota yang berlawanan, semuanya harus terjadi dalam unit sembilanan
(cf. Tichelman 1922; Duyvendak 1927: 78-79; van Rees 1866 : 106; Valentijn
1862, II : 87). Jadi Hualu, yang
termasuk dalam kelompok lima, dibagi dalam 5 unit politik utama; yang membayar
nikah dan denda mereka dalam kelipatan lima; ritual-ritual mereka melibatkan
penggunaan urutan lima kali lipat; mereka juga sering menggunakan formula yang
diakhiri dengan perhitungan “1,2,3,4,5”, dimana 5 indeks penyelesaian suatu
proses, mencapai keseluruhan. Yang sangat menarik adalah fakta bahwa
aturan-aturan ini menyiratkan ketidakmungkinan komunikasi antara kelompok
sembilan dan kelompok lima: sebagai akibatnya, bagaimana pernikahan dapat
terjadi atau denda yang harus dibayar untuk menyelesaikan konflik antara kedua
kelompok ini, ketika masing-masing diminta untuk membayar atau dibayar menurut
rumus berbeda???. Memang, kedua moieties ini (atau lebih tepatnya) adalah endogami,
dan satu-satunya hubungan yang mungkin di antara mereka ada perang; mereka
adalah “musuh lama/alami” (Tiele-Heeres 1868, I: 204; van der Craab 1862 : 212;
Ludeking 1868 :59).
Secara
umum, juga diakui bahwa Lima, secara konspetual
adalah “imigran” terhubung dengan arah ke laut, sedangkan Siwa, dipahami
sebagai “asli” atau “penduduk asli/pribumi”, dihubungkan dengan arah
pedalaman/pegunungan (van Ekris 1861: 319; Riedel 1886 : 90; Jensen 1948: 50).
Oposisi ini memotivasi, atau terhubung dengan yang lain : meskipun kaum pagan
dan kaum muslim ditemukan di kedua kelompok, kelompok lima secara paradigma
terhubung dengan Islam, sebuah agama asing (misalnya, Valentijn 1862, II: 821),
sementara kelompok sembilan itu secara paradigmatik setara dengan agama
tradisional. Kemudian, ketika pertama kali, Portugis, dan kemudian Belanda,
menggunakan kelompok sembilan untuk melawan kelompk lima yang muslim (Tiele –
Heeres 1886, I:96; 204; 244 dll), kesetaraan paradigmatik dibangun antara agama
Kristen dan agama tradisional (Wessels 1934 : 29-30; cf. Rumphius Ms: 191). Memang,
baik orang Seram maupun Belanda bermain-main dengan gagasan bahwa kedua agama
itu, memiliki banyak kesamaan terutama pada kurangnya pelarangan pada daging
babi (Tiele – Heeres 1886, I: 196-197; 205).
Fakta-fakta
ini mengkondisikan sejarah konversi yang
berurutan : kelompok sembilan cenderung untuk beralih pada agama Kristen,
sementara kelompok lima cenderung untuk masuk Islam. Kesetaraan paradigmatik
dari moietis dan relasi eksternal masih kuat dipegang oleh kaum pagan di Hualu,
dimana saya diberitahu : “Kami tidak berniat untuk bertobat; tetapi jika kita
harus melakukan itu, maka itu akan ke agama Islam, bukan ke Kristen, karena
kami adalah Lima !! ”.
Oposisi
lain yang terkait dengan 2 kelompok adalah laki-laki/perempuan, kanan/kiri,
hitam/putih, hidup/mati, dan lain-lain. Namun, korelasi masing-masing istilah
dengan kelompok sembilan atau kelompok lima bervariasi dari satu daerah ke
daerah lain.
Di Seram Barat, misalnya, istilah pertama
(dan superior) dari setiap pasangan dikaitkan dengan Siwa
(Jensen 1948: 46,53,72, 231-232); tetapi di Ambon – atau lebih tepatnya
wilayah-wilayah tertentu – kelompok sembilan dianggap sebagai perempuan, dan
kelompok lima
dianggap sebagai laki-laki (Manusama 1977: 34-35). Di Seram tengah, gender
nampaknya tidak berperan dalam konseptualisasi kelompok Siwa/Lima.
Tanda
signifikan lainnya dari 2 kelompok adalah penggunaan artefak yang berbeda
(Tauern 1918: 43), pakaian, hiasan kepala (Jensen 1948: 93), tarian, musik,
dekorasi tubuh, dan lain-lain. Tanda-tanda ini menciptakan identitas yang lebih
besar daripada yang disediakan oleh bahasa atau adat setempat – yang pada
kenyataannya, mereka mengindeks entitas metatribal yang kadang-kadang bisa
dimobilisasi secara politis oleh para pemimpin.
2
penjelasan dari sistem Siwa/Lima telah dikemukakan.
Yang paling baru adalah milik Duyvendack (1927), yang mengklaim bahwa Siwa/Lima
berasal sebagai suatu sistem moieties eksogami. Namun, tesis ini bertentangan
dengan fakta bahwa kelompok siwa dan lima, tidak
pernah diketahui eksogami, dan juga fakta bahwa kelompok eksogami adalah “asing”
di Maluku Tengah. Tidak perlu untuk menjelaskan dualisme saat ini dengan
mengacu pada masa lalu dari kelompok eksogami, karena prinsip dualisme ada
secara mandiri dan dapat diterapkan pada berbagai situasi sosial, seperti yang
telah kita lihat.
Penjelasan
tradisional dari pandangan sistem itu sebagai cerminan mekanis dari konflik eksternal
antara kesultanan Ternate dan Tidore (Rumphius Ms : 197; 201; Valentijn 1862, I:
249). Konflik ini tentu saja melibatkan dengan konflik dari 2 kelompok dan 2
konflik yang saling memperkuat satu sama lain – tetapi refleksi sederhana dari
satu ke yang lain tidak pernah ada. Selain itu, sistem Siwa/Lima
juga ada di daerah-daerah – seperti Banda, Kei dan Aru – dimana kedua
kesultanan tidak pernah memperluas pengaruh mereka, setidaknya secara
langsung (cf. Van der Chijs 1886 :
73-74). Juga, implikasi umum dari teori ini, bahwa satu kelompok dikaitkan
dengan indeks sembilan
karena kesultanan dibagi menjadi 9 unit – sedangkan
yang lain adalah “lima” karena struktur kelipatan lima dari kesultanan cocok
dengan itu (cf. Rumphius 1910, 1:16; Ludeking 1816 : 56) jelas-jelas salah. Di
tempat pertama, kesultanan-kesultanan tampaknya telah berubah sisi dalam
perjalanan waktu. Awalnya, Ternate dikaitkan dengan Lima, Tidore
dikaitkan dengan Siwa (Tiele-Heeres
1886, 1: 7; Rumphius Ms: 83,191,201; Valentijn 1862, I: 249, 239; Brouwer
(1612) dalam van der Chijs 1886: 62; cf van Ekris 1861: 314). Namun, kemudian,
relasi yang berlawanan juga dilaporkan (cf. Riedel 1886 : 88). Sultan Ternate
sendiri - setidaknya sejak ia menjadi sekutu Belanda – mengklaim kekuasaan pada
anggota-anggota dari kedua kelompok, seperti dinyatakan melalui surat-suratnya
atau pernyataan kepada para pemimpin Maluku Tengah (Tiele-Heeres 1886 – 1895,
I: 150-151, III: 154, 155, 156, 157-158, 204, 209 – 210; de Jonge 1862-1909,
III: 317-318; de Vlamingh van Oudshoorn Ms: 7).
Di
tempat kedua, meskipun sedikit yang diketahui tentang struktur internal Tidore
(ENI IV: 321), tidak ada alasan untuk meragukan bahwa itu mirip juga dengan
Ternate (cf. Van der Crab 1862 : 319 – 320).
Saya
telah mengatakan di atas bahwa identitas metatribal dari kelompok lima dan
siwa dapat
dimobilisasi secara politik oleh para pemimpin. Saya ingin menyebutkan beberapa
fakta yang menunjukan bahwa ini adalah masalahnya; memang, bahwa sistem siwa/lima tidak
dapat dipisahkan dari jaringan politik dan pertukaran regional yang tertarik di
sekitar pusat hegemonik, yang pada gilirannya terkait satu sama lain.
Mari,
saya mulai dengan area yang lebih langsung terlibat dalam lalu lintas
rempah-rempah dan komoditas berharga lainnya, yaitu Ambon, semenanjung Hoamoal
di Seram dan Banda. Di Ambon, praktisnya, semua kelompok lima (di sana disebut Ulilima)
adalah salah satu anggotanya dari konfederasi (bernama Hitu) yang diperintah
oleh 4 pemimpin (disebut perdana – sebuah gelar Jawa – oleh
sejarahwan Hitu abad ke-17, Rijali), atau mengakui hegemoni para kepala ini,
membantu mereka berperang, dan menggunakan markas mereka – desa/negeri Hitulama
– sebagai tempat penjualan rempah-rempah. Hitulama didirikan pada paruh kedua
abad ke-15 oleh nenek moyang dari 4 garis keturunan di mana para perdana adalah
anggota-anggotanya. Asal mereka adalah orang asing dan menghubungkan mereka
dengan beberapa pusat perdagangan dan kekuasaan utama, tidak hanya di Maluku,
tetapi juga di Jawa : pesisir tenggara Seram, kesultanan Jailolo (yang sampai
dihancurkan oleh Ternate, adalah yang tertinggi di antara 4 kesultanan Maluku),
dan kesultanan Tuban di Jawa.
Meskipun
pemerintah dari 4 perdana
– dalam kata-kata Rumphius – “aristokratik” (yaitu,
oligarki; Rumphius Ms: 10), sentralisasi berkembang dengan perluasan kekuatan
Hitu. Rijali melaporkan bahwa pada sekitar tahun 1510, setelah kembalinya seorang
warga negara penting dari Jawa, diputuskan untuk memiliki raja permanen (Latu Sitania),
yang akan menjadi trait
d’union di antara perdana maupun
antara perdana
dan rakyat (Rijali HTH, X; Rumphius Ms; 14;
Manusama 1977 : 30-31).
Kedatangan Portugis memperkuat
kepemimpinan Hitu atas semua kelompok lima
di Ambon, pada awalnya orang-orang
Lusitanian (Portugis) memilih untuk berdagang di Hitu, kemudian karena mereka
menjadi musuh dan memihak kelompok siwa melawan
kelompok lima (cf. Valentijn 1862, II
: 131,133; Rijali HTH, XV; Rumphius Ms: 44-49; 46; Manusama 1977: 40 – 43). Dengan
demikian, semakin banyak lima yang
dipaksa berpihak pada Hitu. Hanya Belanda yang berhasil menghancurkan kekuatan
Hitu – tetapi tidak menghilangkan afiliasi keagamaannya (Islam).
Situasi yang mirip dengan Ambon,
ada di semenanjung Hoamoal (Seram) yang berdekatan, juga merupakan pusat
penting produksi dan perdagangan cengkih (dan pala). Luhu adalah pemimpin 17
komunitas di pantai timur semenanjung itu. Seperti Hitu, Luhu diperintah oleh 4
kepala dan primus inter pares dari 4 “garis
keturunan” utama (Rumphius Ms: 101-102; Valentijn 1862, II: 49 – 50). Seperti
di Hitu, struktur 4 + 1 dari pusat kekuasaan ini menunjukan bahwa Luhu termasuk
dalam kelompok lima.
Komunitas penghasil cengkih di
pantai barat Hoamoal berada di bawah kepemimpinan 3 pusat kekuasaan, Kambelo,
Lesidi dan Asahudi, semuanya adalah siwa (Valentijn
1862, I: 245, II: 40 – 46).
Kepulauan Banda, di tenggara
Ambon, adalah pusat utama untuk produksi dan perdagangan pala. Wilayah itu juga
dibagi menjadi kelompok siwa (disebut
Ursiwa) dan kelompok lima (disebut Urlima). Menurut pengunjung Belanda pertama (1599), masing-masing
kelompok mencakup 6 atau 7 “kota” (van Heemskerk dalam de Jonge 1862 – 1909, II
: 427, cf. Halaman 172), suatu situasi yang mengingatkan kita pada situasi
Ambon, di mana Hitu termasuk 7 ulilima, yaitu
kelompok-kelompok yang dibagi dalam five (lima) unit (Uli).
Fitur lain dari Banda yang
mengingatkan situasi di Hitu adalah kehadiran “4 raja” (Valentijn 1862, III:
29, 290-291; Beschrijvinge 1855 : 78). Raja-raja ini, yang disebutkan dalam
kontrak pertama (160 – 162) antara VOC dan orang-orang Banda (de Jonge
1862-1909, II : 536 SV; Heeres-Stapel 1907 : 23; van der Chijs 1866 : 169 –
170) tampaknya semua adalah kelompok lima7.
Dengan demikian kelompok lima Banda,
seperti rekan-rekan mereka di Ambon, dipimpin oleh 4 pemimpin/kepala, salah
satunya mungkin adalah ketua/penguasa tertinggi.
Aspek komersial dari persaingan Siwa dan Lima tampaknya telah menjadi dominan di Banda : kita diberitahu bahwa
mereka memperebutkan kendali atas bea pelabuhan, yang dibagikan oleh semua
anggota kelompok (van der Chijs 1886: 5; de Jonge 1862 – 1909, I : 172, 427)8.
Sistem Siwa/Lima juga ditemukan di
kepulauan Kei dan Aru, yang berada di selatan kepulauan Banda. Meskipun
masyarakat ini merupakan masyarakat lebih “pinggiran” dalam sistem perdagangan
inter insular, mereka dikonfirmasikan bahwa pemimpin setiap kelompok, cenderung
menjadi penguasa pusat komersial. Dengan demikian kepala/pemimpin dari 2 pusat
pesisir tersebut telah berhasil diakui sebagai pemimpin masing masing dari
semua kelompok lima dan siwa di Aru (Brumund 1845 : 289-290; van
Eijbergen 1864: 557-558; 1866: 299; Muler Ms).
Sayangnya, di Kei, situasinya
jauh kurang jelas karena, ketika penelitian serius dimulai, sistem siwa/lima telah berhenti berfungsi atau bahkan
diingat dengan cara koheren (cf. Van Hoevell 1890; Nutz 1959: 89). Namun, kita
tahu bahwa ada persaingan di antara penguasa asli untuk kepemimpinan
masing-masing kelompok. Jadi raja-raja Wain, Danar dan Dulah – semuanya berkepentingan
dalam perdagangan – mengklaim kepemimpinan siwa
pada waktu berbeda (Bosscher 1855: 23-26; van Eijbergen 1866: 254,
268-269). Perhatikan juga bahwa Kei maupun Aru, secara tradisional tertarik di
sekitar Banda yang merupakan pasar untuk sejumlah produk mereka (cf. Barchewitz
1730: 146-149; de Klerk 1894: 29-36). Hal ini dan kehadiran komunitas-komunitas
Banda di Kei, mungkin menjelaskan kesamaan yang kuat antara sistem siwa/lima di daerah pinggiran ini, dan
sistem di daerah “tengah” yaitu Ambon dan Banda.
Situasinya
jauh lebih kompleks dan bervariasi di Seram. Wilayah pesisir secara budaya dan
politik dekat dengan wilayah yang telah kita pertimbangkan sejauh ini; tetapi
kontrol atau pengaruh mereka terhadap populasi pedalaman sangat bervariasi dan
tidak ada yang total. Mempertimbangkan hanya Seram Tengah dan Barat, kita
melihat bahwa daerah yang dulu, mungkin adalah tempat dimana pengaruh politik
dan budaya dari pesisir paling besar. Di Seram Tengah bagian selatan, ada
sejumlah kekuatan yang asal-usulnya terhubungan dengan penanaman rempah-rempah
dan perdagangan dan dimana unsur-unsur asing terlihat. Sebagai contoh, salah
satu desa di teluk Teluti di sebut Kota Mahu: ini menunjukan bahwa
desa itu dihuni oleh orang-orang asal Jawa (disebut Mahu di Seram, cf.
Valentijn 1862, II: 72). Pengaruh orang-orang Banda juga menonjol (cf. Verbeet
1762: 33; van der Chijs 1886: 99-100; catatan lapangan Valeri). Organisasi
politik kelompok-kelompok ini sangat mirip dengan Ulisiwa / Ulilima Ambon.
Adapun suku-suku pegunungan/pedalaman, mereka berada dibawah hegemoni Latu
(Raja) Manusela, yang merupakan siwa, dan mengklaim
merupakan keturunan dari keluarga penguasa Ternate. Dia (dan ) juga secara
mitologis terhubung dengan Sahulau, seorang Raja dari
Seram Barat, dimana ia juga sendiri terkait dengan Ternate (catatan lapangan
Valeri; Roder 1948: 15; Valentijn 1862, II: 82).
Pantai
Utara Seram dan daerah pedalamannya berada dibawah pengaruh kesultanan Bacan9
(seperti yang diungkapkan oleh legenda-legenda yang saya kumpulkan di Nisawele)
antara lain (cf. Rumphius Ms: 116-117; Valentijn 1862, I: 266, 270-271, I:58)
dan lebih langsung dibawah komunitas Lisabata – didirikan oleh orang asing dari
berbagai asal dan mengklaim hubungan dengan kesultanan Gilolo dan dengan Hitu (Valentijn
1862, II: 55-56; Rumphius Ms: 111-112, 113, 114-115). Seperti yang terakhir,
Lisabata adalah Muslim dan Lima. Agaknya kehadiran
wilayah lima yang
luas antara siwa Seram
Barat dan siwa Seram
Tengah, dalam beberapa hal berhubungan dengan hegemoni Lisabata di wilayah ini.
Hegemoni ini sering melibatkan pemaksaan upeti dan deportasi desa-desa
(Valentijn 1862, 11: 58). Akibatnya, salah satu “rumah” Hualu, pada awalnya
adalah kelompok siwa di
Seram Barat, tetapi “takluk” dibawah pengaruh Lisabata, dan akibatnya menjadi lima serta
harus mengikuti “tuannya” ketika mereka pindah ke Seram Tengah (Valentijn 1862,
II: 57)
Situasi
paling kompleks adalah di Seram Barat. Berbagai suku pedalaman dan sebagian
besar kelompok pesisir juga adalah siwa. Mereka terbagi dalam
3 konfederasi, masing-masing dibawah kepemimpinan seorang Kapitan. Dalam
hal perang, anggota dari masing-masing konfederasi bertemu di salah satu dari 3
sungai : Eti,
Tala dan Sapalewa. Tetapi disamping para
penguasa tradisional ini, rangkaian 3 penguasa baru berkembang, khususnya
karena pada abad ke-17, Belanda menggunakannya sebagai sarana merekrut siwa Seram
Barat untuk keperluan militer mereka sendiri (cf. De Vlamingh van Oudshoorn Ms:
119 verso). Ketiga penguasa ini adalah Sahulau yang disebut sebelumnya, dan
“raja-raja” dari Sumit dan Siseulu (Valentijn 1862, II: 72-75, 78-79, 80-84).
Mereka semua memiliki koneksi dengan kekuatan dari luar dan menemukan
legitimasi mereka melalui hal itu.
Untuk menyimpulkan survei
yang terlalu singkat ini, saya harus menambahkan bahwa sebagian besar pusat
politik yang disebutkan di atas terkait satu dengan yang lain, melalui aliansi
atau keturunan bersama. Jadi, misalnya, baik penguasa Lisabata dan salah satu
garis keturunan utama perdana Hitu, mengklaim
merupakan keturunan dari 2 orang bersaudara, yang pada gilirannya adalah
anggota garis keturunan kerajaan Jailolo. Selain itu, mereka juga memiliki
koneksi dengan wilayah Luhu, melalui leluhur bersama lainnya. Menurut versi lain,
semua penguasa ini terhubung dengan Sultan Bacan (Valentijn 1862, I: 236,
270-271; II: 55-56; cf. Manusama 1977: 21). Hitu juga memiliki koneksi dengan
kelompok lima Seram
Selatan (Valentijn 1862, 1: 240; 11: 69-70; Rumphius 1910, 1: 83), dan menjalin
aliansi politik dengan kelompok lima Banda (van
Vollenhoven 11: 792) serta dengan Sultan Ternate (Rijali HTH, VIII; Valentijn
1862, I: 240). Singkatnya Latu Sitania dan empat perdana Hitu
berada di pusat jaringan politik yang luas, yang menghubungkan sebagian besar
kelompok lima Maluku
dari Banda ke Seram Tengah.
Tidak ada jaringan
yang sebanding tampaknya ada di antara kelompok siwa, meskipun
Sahulau dan Latu Manusela – dua pemimpin utama Siwa Seram
– secara ideologis terkait. Di sisi lain, Belanda, yang dianggap oleh orang
Seram sebagai siwa (Rumphius
1910, I: 84), mungkin juga dipandang oleh banyak orang sebagai pemimpin mereka,
setidaknya pada abad ke-17.
Perlu juga disebutkan
bahwa Sultan Ternate memiliki para Kimelaha, “Gubernur” di
Maluku Tengah, khususnya di Buru dan di Luhu (Hoamoal). Pada paruh kedua abad
ke-16, para kimelaha ini telah menggantikan sebagian hegemoni lokal dalam
kontrol politik perdagangan (Valentijn 1862, II: 7, 50-51; Rumphius Ms:
200-203; Hustaart Ms: 147). Kimelaha dari Luhu dan Buru adalah anggota dari
garis keturunan Tomagola, yang oleh banyak orang di Seram dan Ambon diklaim
memiliki koneksi. Sebagai contoh, Tamatay, salah satu
“rumah/lumah” Hualu, mengklaim terkait dengan garis keturunan ini. Bukti di
atas telah menunjukan bahwa sistem siwa/lima – apapun asalnya –
pasti digeneralisasi dan diubah bentuknya dibawah pengaruh jaringan kekuatan
pesisir, diantaranya kita harus menempatkannya, setidaknya pada abad ke-16 dan
sebagain abad ke-17. Sangatlah menarik bahwa dalam banyak mitos Seram, yang
telah saya baca atau kumpulkan sendiri, asal usul sistem siwa/lima terhubung
dengan beberapa penguasa ini. Tentu saja di Seram Tengah, sistem itu dipandang
sebagai pembagian sewenang-wenang, yang diperkenalkan oleh Latu Sahulau atau
oleh Latu Siale. Yang terakhir (Latu Siale – maksudnya) adalah salah satu
penguasa pertama Ternate (Valentijn 1862, I: 283) dan namanya identik dengan
tanjung paling selatan semenanjung Hoamoal (maksudnya tanjung sial – catatan
tambahan dari kami), yang juga merupakan pusat kekuasaan Ternate di Seram.
Setidaknya penduduk
Seram Tengah (sebagaimana banyak masyarakat pesisir di berbagai bagian pulau
Seram), kemudian mengakui bahwa dalam bentuknya yang sekarang, sistem ini tidak
dapat dipisahkan dari jaringan pusat-pusat politik yang disebutkan di atas.
Bahkan, orang-orang Seram bagian Barat, seperti yang akan kita lihat, mengakui
fakta ini dalam mitos-mitos mereka, meskipun mereka kurang menonjolkannya.
Pengaruh pusat-pusat ini pada sistem siwa/lima
juga ideologis. Memang, ada indikasi kuat bahwa di Seram Tengah, setidaknya
ideologi siwa/lima adalah adaptasi
lokal dan transformasi kreatif dari ideologi yang berkembang di wilayah-wilayah
pesisir – khususnya di Ambon dan Hoamoal yang terkait erat. Karena itu, kita
harus “menengok” ke ideologi orang-orang Ambon ini, sebelum mempertimbangkan
padanan dari sistem ini pada orang-orang Seram.
=====
bersambung =====
Catatan kaki
- Seorang Raja adalah penguasa “kota-kota” Dender dan Rosengain; yang lainnya memerintah Labetaka, Waier dan Salama. Sejak itu dan menurut laporan yang akurat (Beschrijvinge 1855), “kota-kota” itu semuanya disebut sebagai kelompok lima – kecuali Labetaka yang pada masa itu menjadi kelompok siwa – saya (penulis) menyimpulkan bahwa 4 raja itu adalah kelompok lima / urlima
- Perkembangan perdagangan nampaknya menghasilkan oposisi politik di Banda dan Hitu. Di Hitu, hal demikian dipaksakan untuk tersentralisasi, sedangkan di Banda, hal itu membuat jatuhnya 4 raja itu, yang mana kedudukan mereka digantikan oleh oligarki perdagangan, dimana masing-masing kota dipimpin oleh shabandar dan oleh penguasa beragama islam (de Jonge 1862-1909, II: 427-428, Beschrijvinge 1855: 78; Valentijn 1862, III: 29-30). Selanjutnya kontrak-kontrak dari tahun 1605 dan 1609 terus menyebut raja-raja dan hanya menyebut “kota-kota” ( de Jonge 1862-1909, III : 210 sv, 325 sv). Rezim ini, dalam kata-kata Matelief – pengunjung Belanda – sebagai “republik” (van der Chijs 1886: 33)
- Juga oleh suatu fakta bahwa salah satu pemimpin komunitas di wilayah ini menggunakan nama Besi, yang merupakan nama lain dari Bacan (cf. Van der Crab (ed) 1878 : 437)



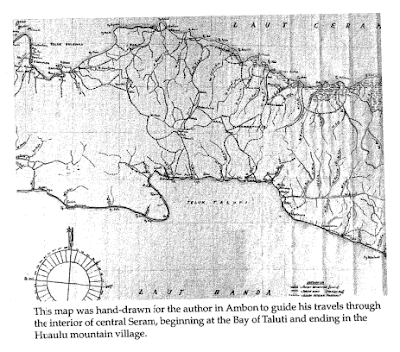

Tidak ada komentar:
Posting Komentar